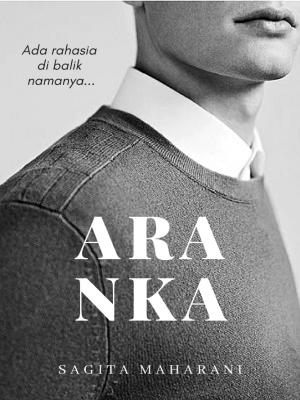Ibu. Satu kata penuh makna dan cinta. Engkau mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanku, perjuanganmu sungguh tak akan hilang tergerus waktu. Aku sangat menyayangimu. Ibu yang selalu medekapku setiap malam, Ibu yang mencintaiku dalam keadaan apapun. Ibu adalah pahlawanku. Meskipun Ayah telah pergi ke Surga, engkau masih tetap tersenyum. Aku tahu itu perih, sangat perih. Senyum lembutmu selalu kau beri padaku, entah saat kau terluka ataupun bahagia. Masih jelas dalam ingatan saat engkau menggendongku melawan hujan, berharap masih ada klinik yang mampu membantuku sembuh dari penyakit.
Seiring berjalannya waktu, aku tumbuh menginjak usia dewasa, begitupun Ibu yang semakin menua. Meski begitu, Ibu masih tetap bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup kami. Semangatmu adalah api yang tak pernah padam. Aku mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu dengan menghadirkannya di dalam hidupku. Saat jarum jam menunjuk pukul 7.00 WIB, Ibu mengantarku ke sekolah. Memberi bekal makan dan mendoakanku agar belajar dengan rajin. Tatkala aku pulang ke rumah, engkau akan memberiku pelukan hangat dan sejuta kecupan penuh cinta. Terkadang aku kesal karena Ibu memperlakukan aku seperti anak TK, beribu protes kuajukan tapi Ibu tak pernah menanggapi. Engkau selalu menjawab, “ Diana sayangku, bagiku kamu akan selalu menjadi putri kecilku”.
Hari ini tepat di usiamu yang ke lima puluh tahun, aku pulang bergandengan tangan dengan seorang pria. Tatapanmu mulai sendu namun engkau masih tersenyum menyambut kedatangan kami. “ Bu, ini Dika. Dia adalah pria yang sering aku ceritakan padamu”, aku mengenalkannya dengan sejuta kebahagiaan. Tangan keriputmu menyentuh tangannya, “ Nak Dika, apa Diana merepotkanmu?”. Pertanyaanmu sungguh membuat kami terhenyak, aku berpandangan dengan Dika. Namun, Dika mengelus tanganku mencoba meyakinkan bahwa dia dapat menjawab pertanyaanmu dengan baik. “ Diana anak yang baik, Bu. Saya ingin membina hubungan yang serius dengannya, apakah Ibu merestui hubungan kami?”. Hatiku berdebar-debar, berbagai pertanyaan mulai mencuat dalam otakku. Akankah Ibu merestui kami? Ataukah sebaliknya? Memikirkannya saja sudah membuatku sakit kepala.
Hanya sebuah anggukan yang engkau berikan, namun entah mengapa terasa sangat membahagiakan. Di malam hari, engkau datang ke kamarku dengan membawa sebuah album foto. Engkau duduk di sisiku, tepat di samping meja belajar. “ Diana, Ibu ingin kau melihat ini”. Ibu menceritakan semuanya padaku. Siapa dan bagaimana aku ketika masih kecil. Malam itu kami menghabiskan waktu dengan berbagi cerita masa lalu. Saat itulah aku tersadar bahwa waktu berjalan begitu cepat.
Perlahan aku mulai mengerti mengapa kala itu senyuman Ibu memudar, mungkin karena sebuah kenyataan pahit bahwa suatu saat nanti aku akan pergi dari rumah. Bayangkan saja bagaimana perjuangan dan pengorbanan Ibuku saat harus mendidik dan membesarkan aku seorang diri. Ibu mana yang tak bersedih saat harus melepas anaknya? Terlebih aku adalah anak tunggal.
Malam itu setelah Ibu pergi dari kamarku, aku duduk merenung di tepi ranjang. Perlahan ku baringkan tubuh dan menutup mata, aku tertidur dalam kecemasan.
Sinar mentari masuk melalui celah-celah gorden kamarku, aku membuka mata. Berjalan ke arah jendela dan ku sibak gorden itu, seketika sinar mentari memenuhi kamarku. Silau.
Krek. Pintu balkon terbuka, harum tanah membuat aku merasa tenang. Aku berjalan menuju sisi balkon, menatap hamparan kebun bunga milik Ibu. Sangat indah. Sebuah senyum ku ulas, mungkin orang lain akan iri denganku.
Tes. Tetesan air mengenai telapak tanganku. Aku heran dibuatnya, cuaca secerah ini namun mengapa ada hujan? Ah, aku mengangguk lalu tertawa. Ternyata ini bukan hujan tapi air mataku. “ Hujan macam apa yang datang dari mata manusia?”, aku berbicara pada alam. Tentu tak akan ada jawaban namun biarlah ini menjadi obrolan sepihak, alam hanya perlu mendengar.
Tadi malam sungguh indah sampai aku kehabisan kata untuk berdo’a. Ya, berdo’a agar itu semua mejadi kenyataan. Karena faktanya setiap hari aku selalu berandai-andai akan seindah apa jika Ibu ada di sini. Bunga tidurku yang semalam-pun tak kalah indah, semua terasa sangat nyata. Aku terkekeh sambil menyeka air mata yang jatuh.
Tangisku semakin hebat hingga bernapas-pun menjadi sulit. Benar kata orang bahwa kenyataan selalu lebih pahit dari bayangan. Ibu? Masih pantaskah wanita itu disebut Ibu? Sungguh panggilan yang menggelikan. Ia bahkan tidak pantas disebut manusia.
Ibu adalah kemustahilan yang nyata. Tidak pernah ada pelukan atau senyuman lembut. Semua itu hanyalah kebahagiaan dalam kedok kepalsuan. Aku terduduk lesu di lantai. “ Diana yang malang”, aku memukul-mukul kepalaku dengan tempo lambat.
Aku membencinya namun aku juga merindukannya. Aku juga ingin punya ibu. Ibu yang mencintaiku, bukan Ibu yang membuangku ke panti asuhan.
Momen itu akan selalu ku ingat jelas. Saat aku diam-diam mulai mencari keberadaan kalian, orangtuaku. Berbagai fakta pahit terus ku telan bulat-bulat. Aku adalah Diana, putri seorang penjudi. Aku adalah Diana, anak yang tidak cukup berharga untuk dipertahankan.
Di bawah teriknya matahari, aku menggenggam sebuah foto. Mencari hingga peluh berjatuhan. Tepat di lampu merah aku melihatmu, Ayah. Engkau yang sedang memalak seorang remaja, engkau yang bahkan berpakaian tak karuan. Kecewa. Aku tidak jadi menyapamu.
Aku masih ingat saat langkah kaki ini berjalan ke sebuah perumahan elit. Aku datang ke rumahmu, Ibu. Sebuah pigura besar menyambutku, engkau yang tersenyum bahagia dengan keluarga barumu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. “Ayo sini! Kamu mau melamar jadi pembantu kan?”, ucap seorang wanita berpakaian sederhana. Dari kejauhan, aku melihatmu menuruni tangga dengan anggun. Semua yang kau kenakan begitu mewah, lalu aku melihat pada diriku sendiri. Aku kumuh. Pantas saja dianggap ingin melamar kerja menjadi pembantu. “ Kau terlalu kumuh untuk jadi pembantu di rumah ini”, ucap Ibu penuh keangkuhan. “ Ibu”, aku menggenggam tangannya dengan berurai air mata. “ Singkirkan tangan baumu dan pergi dari tempat ini”, Ibu pergi meninggalkanku. Dengan langkah gontai aku pergi dari rumah mewahmu. Ku tolehkan mata ke arah rumahmu dan aku menyesal. Aku menyesal karena melihatmu tersenyum dan memeluk seorang anak laki-laki. Aku bahkan belum sempat mengatakan bahwa kamu adalah Ibuku, namun sepertinya ada atau tidaknya aku tidak penting bagimu atau mungkin suatu saat nanti engkau akan mencariku untuk dilenyapkan agar tidak mengusik kebahagiaanmu.
Entah sejak kapan aku sudah berbaring di atas lantai balkon, menangis dalam diam. Aku rindu kehangatan keluarga. Aku ingin berbagi tangis dan tawa dengan Ayah dan Ibu. Satu-satunya sosok Ibu dalam hidupku adalah Ibu Panti yang kini juga pergi menghadap Tuhan. Aku sendirian. Jika aku mengingat bagaimana Ayah dan Ibu hidup saat ini, aku ingin egois. Aku ingin suatu saat nanti kalian merasakan apa itu penyesalan. Aku ingin Ayah merasakan sakit sepertiku. Aku ingin Ibu menangis meraung-raung dan memintaku kembali. Biarlah permintaanku ini dianggap sangat jahat karena bagiku kalian jauh lebih jahat. Tetapi di sudut hatiku yang terdalam, aku selalu berharap kehadiran kalian. Mencintai dan membenci secara bersamaan adalah “kutukan” paling menyedihkan. Lebih menyedihkannya, aku adalah manusia terpilih yang didaulat untuk merasakan “kutukan” itu.


 Fakhdania
Fakhdania