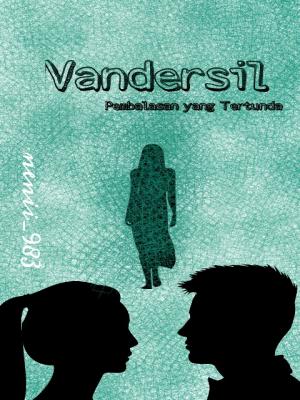Kemarin aku terbangun tanpa tahu apa-apa, kecuali satu hal––aku baru saja sah menyandang umur enam belas tahun.
Aku tidak ingat kenapa bisa ada di rumah sakit. Agak kaget saat pertama kali kulihat terdapat beberapa luka di area lengan baik itu sebelah kanan maupun kiri. Terlebih lagi saat aku menyadari kalau kepalaku sudah dalam keadaan diperban. Tampaknya ada suatu hal luar biasa yang telah datang menimpaku dan aku sama sekali belum mendapat penjelasan soal itu.
Suster yang sekarang sedang berdiri di sebelah tempat tidurku juga tidak mengatakan apapun. Setiap kali datang, dia hanya menyapa sambil tersenyum manis, menanyakan bagaimana keadaanku, kemudian langsung memeriksa kondisi tubuhku. Kalaupun aku yang inisiatif bertanya, percuma. Jawaban yang diberikan juga tidak memuaskan.
Lagi pula di mana ayah dan ibu? Sejak kemarin keberadaannya sama sekali belum terlihat. Bukan kah seharusnya mereka ikut mendampingiku di sini? Apa ayah dan ibu tidak khawatir? Tidak bermaksud menungguku sadar? Malahan aku lebih sering melihat seorang lelaki tak dikenal berdiri di luar pintu dalam rentang waktu––mungkin ada sekitar dua jam sekali. Entah dia sedang berbicara dengan siapa di luar sana. Raut wajahnya tampak serius. Sesekali pula dia menengok ke arahku dan tersenyum tipis. Heran. Apa aku yang masih anak sekolahan ini terlihat begitu mempesona, sehingga dia langsung melontarkan senyuman padaku walau baru pertama kali melihat? Aku jadi geleng-geleng kepala sambil menahan tawa sewaktu pikiran itu terlintas di kepala.
Dan sekarang aku mulai merasa bosan. Setelah suster pergi meninggalkanku sendirian lagi di dalam kamar, aku pun mulai merasa bosan. Untuk dihuni satu orang pasien, ruang kamar ini terbilang cukup besar. Alhasil hanya menghadirkan suasana dingin juga sepi di setiap detiknya. Bahkan saking sunyinya, suara engsel pintu bergerak pun sampai terdengar begitu jelas.
***
“Maaf ya kita ngga bawa apa-apa. Sekarang udah baikan belum?”
Ya Tuhan. Padahal di kelas selalu bertemu, tapi rasanya seperti sudah sangat lama tidak melihat dua orang ini.
“Heh malah bengong!” seru Moura sambil menepuk pipiku.
Tepukannya terasa bagaikan tersentuh kapas halus. Membuatku merasa nyaman. Apalagi ditambah dengan hadirnya sesosok lelaki tampan berseragam sekolah yang berdiri gagah di sebelah tempat tidurku. Membuatku lebih merasa nyaman juga lebih bersemangat. Glend sifatnya memang agak dingin, tapi dia tetap perhatian. Dan jujur saja, selama ini diam-diam aku menyukainya.
Setelah mata jernih milik Glend menyusuri sekeliling kamar, barulah dia menatapku.
“Jadi, kapan bisa pulang?” tanyanya dengan gaya andalan miliknya. Dari sekian banyak hal yang bisa dia lakukan, yang paling kunanti adalah saat dia bicara sambil menatapku. Itu saja.
“Mungkin dua atau tiga hari lagi. Dokter bilang masih ada yang harus diperiksa. Kelihatannya sih cuma dapat luka luar, tapi kupikir pasti juga ada luka dalam.” jelasku mendadak murung.
Sebenarnya aku tidak bermaksud ingin mengubah suasana menjadi lebih buruk dan seharusnya mereka berdua juga tidak perlu jadi saling diam ketika tahu bagaimana responku. Pokoknya aku paling tidak suka kalau Glend dan Moura tidak berdebat seperti biasanya. Kalau mereka berdua sudah saling menutup mulut, sudah pasti ada sesuatu yang terjadi.
“Kalian berantem ya?” lanjutku bertanya.
Mereka pun saling menatap satu sama lain dengan ekspresi mengelak milik masing-masing. Sepintar apapun mereka dalam meyakinkanku bahwa tidak terjadi apa-apa, semakin aku tahu jika mereka berbohong.
“Udahlah. Moura, kenapa? Glend pasti buat kamu gagal pas mau nyontek, kan?” tanyaku yakin pada Moura, kemudian mengubah arah tatapan pada Glend. “Glend, kenapa? Kalah tanding basket lagi sama Moura?” tanyaku yang benar-benar sudah paham akan semua kebiasaan dari mereka berdua.
Beberapa detik berlalu tetap tak ada tanggapan. Apa pertanyaanku salah? Apa pertanyaanku menyinggung perasaan? Tapi itu tidak pernah terjadi. Kami saling mengerti satu sama lain. Lagi pula hal semacam itu sudah biasa. Glend hampir selalu melakukan itu pada Moura, begitu pun sebaliknya. Sementara aku berperan sebagai penengah di antara mereka. Lantas kali ini ada apa?
Glend duduk di area pinggiran tempat tidur di samping kedua kakiku yang masih tertutup selimut. Dia memandangku sambil menepuk-nepuk kepalaku. Walau senyumannya tipis, aku tetap suka.
“Lo ngga perlu mikirin hal lain. Fokus aja ke kondisi lo sekarang ya.”
“Aku udah baikan kok. Cuma masalahnya adalah aku ngga tau alasan apa yang buat mereka masih menahan aku di sini. Mau cari tau aja susah. Ngga ada satu pun yang mau jelasin.” jelasku mengadu.
“Emangnya apa lagi yang mau lo tau? Kalau orang ada di rumah sakit, udah pasti karena dia sakit. Tuh, liat sendiri, kan? Luka dimana-mana.”
“Ya ngga usah nge-gas juga, Ra.” bela Glend.
Aku pun menghela napas. “Aku tau aku sakit, tapi sakit apa? Penyebabnya apa? Orang tuaku juga ada di mana? Kenapa sampai sekarang mereka ngga jenguk aku di sini? Aneh deh, kenapa aku sama sekali ngga bisa ingat apa yang udah terjadi.”
Glend menangkup kedua punggung tanganku. Tangannya agak dingin. Memangnya sudah berapa hari aku tidak bertemu dengannya? Sampai kaget sendiri ketika tahu kalau telapak tangannya begitu halus.
“Udah ya. Apa yang udah lewat ngga perlu diingat lagi. Sekarang yang penting lo udah sadar. Meskipun gue sama Moura juga ngga tau orang tua lo lagi di mana, tapi gue yakin mereka pasti datang. Lagi pula emangnya belum cukup ada gue di sini?”
Aku kesulitan untuk tidak tersenyum. Rasanya pipiku panas dan memerah.
“Gue keluar dulu.” ujar Moura.
“Loh mau ke mana?”
“Cari angin. Gerah!” teriaknya yang sudah mencapai gagang pintu dan menutupnya dengan cara yang tidak santai. Ingin kutanyakan pada Glend ada apa dengan Moura, sebab dia begitu terlihat emosi hari ini. Namun seperti biasa Glend pasti akan menjawab, “Ngga tau. Ngga jelas.”
***
Aku, Glend, dan Moura bertemu pertama kali ketika hari pertama masuk SMA dan kami bertiga ditakdirkan berada di kelas yang sama. Meskipun sifat kami berbeda satu sama lain, namun anehnya kami bisa dekat dan bisa saling melengkapi. Aku yang dinilai polos, baik juga sabar, kemudian Moura yang tomboi, serta Glend yang agak ketus, tapi perhatian. Entah bagaimana kami bisa menyatu dengan keberagaman itu.
Seiring berjalannya waktu, tidak bisa dipungkiri lagi kalau segala bentuk perhatian Glend padaku telah berhasil menghadirkan rasa baru untuknya. Bukan lagi sekadar rasa pertemanan. Melainkan lebih dari itu dan Moura pun mengetahuinya. Awalnya kupikir Moura tidak setuju bahkan marah, tapi kenyataannya dia justru mendukung dan mengatakan kalau menurutnya Glend juga menyukaiku.
Hanya saja sayangnya rasa gengsi milik masing-masing dari kami terlalu dominan. Jadinya sampai sekarang tidak ada satupun di antara aku dan Glend yang mau mengaku lebih dulu. Membuatku menunggu dan terus menunggu.
“Aku dengar ada anak kelas X yang suka kamu?”
Sial. Belum ada satu menit aku sudah menyesal karena bertanya itu. Tadinya aku bermaksud ingin mencari bahan perbincangan, tapi ternyata sulit. Rasanya canggung. Seperti sudah lama tidak mengobrol berdua dengan Glend.
Wajah Glend masih menunduk pada buku yang dia pegang. Entah buku apa.
“Oya? Kalau ada emangnya kenapa?” wajahnya terangkat ke arahku. “Lo keberatan?”
Kedua mataku langsung melebar. Pertanyaannya barusan benar-benar menekanku.
“Ah ngga.”
“Ngga?” tanyanya memastikan.
Gerak mataku langsung tak fokus. Juga salah tingkah.
“Ya buat apa aku keberatan? Kalau emang dia suka kamu dan kamu suka dia, bagus, kan?” jawabku dimana Glend langsung tersenyum tipis diiringi dengan gerak kepala yang kembali terpaku pada sebuah buku di tangannya.
Bodoh. Selalu saja aku seperti itu. Kapan aku punya keberanian untuk mengatakan kalau aku suka padanya? Kalau aku cemburu dan kesal setiap kali aku tahu bahwa ada perempuan di sekolah yang menyukainya. Kenapa aku begitu tahan untuk terus memendamnya? Begitu pun dengan Glend. Kenapa pula dia selalu saja mengeluarkan perkataan yang ambigu? Selalu saja mengeluarkan pertanyaan yang memancingku untuk mengaku. Kenapa bukan dia saja yang mengaku lebih dulu?
Mungkin ada baiknya kucukupkan sampai di sini.
“Glend, sebenarnya aku mau bilang kalau––”
“Ayo kita pulang.” seru Moura yang tiba-tiba datang tanpa suara.
Tahu-tahu dia sudah berdiri di sampingku dengan raut wajah yang menyeramkan. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu dari mana saja dia dan apa yang baru saja terjadi dengannya sehingga rupanya bisa tampak seperti itu.
“Gue masih mau temenin Mia di sini. Kalau lo mau duluan ngga apa-apa.”
“Mia juga mau istirahat, kali, Glend.” balas Moura tak kalah ketus. Sungguh aku tidak tahu kenapa mereka berdua bersikap seperti ini. Padahal sebelumnya terlihat biasa-biasa saja.
Glend beranjak dari kursi.
“Ok. Coba kita cari tau jawabannya. Jadi, apa lo mau kita––gue pulang?” tanyanya padaku. Terkhusus untuknya, Glend menunjuk dirinya sendiri dengan tegas. Berupaya menarikku untuk menjawab tidak.
Kenapa hal sepele semacam ini bisa berubah menjadi serius? Membuat kepalaku pusing dan mulai berdenyut. Aku pun reflek memegang perban yang melilit di kepala. Mengernyit menahan sakit.
“Mia, lo kenapa?” tanya Moura mendekat. “Udah gue bilang dia butuh istirahat, Glend. Kita mesti pulang.”
“Ngga. Gue masih mau jaga Mia.”
“Pergi!”
Teriakku spontan. Moura dan Glend seketika terpaku di tempat. Sampai akhirnya Glend sadar bahwa bukan mereka berdua orang yang kumaksud. Bukan mereka yang kuminta pergi, sebab kedua mataku justru mengarah lurus pada pintu.
Di tengah kepanikan, yang bercampur dengan kesakitan dan ketakutan, Moura terus-menerus bertanya kenapa seraya menggoyang-goyangkan kedua bahuku. Sementara Glend memilih bergegas pergi memeriksa keadaan di luar kamar untuk mencari tahu apa yang membuatku berteriak ketakutan. Sungguh aku tidak salah lihat. Baru saja lelaki tak dikenal itu muncul di sana––di balik pintu yang tertutup. Dia melihat ke arahku melalui kaca pada pintu sambil mengernyitkan dahi. Benar-benar menyeramkan.
“Ngga ada apa-apa.” jelas Glend sembari berjalan kembali.
Moura melepas tangannya dari bahuku.
“Ngga perlu takut begitu lah. Mungkin bagi lo dia memang orang asing, tapi belum tentu dia punya niat jahat.” ujar Moura seraya melirik Glend. “Malahan bisa jadi orang terdekat yang justru punya niat jahat.”
Glend langsung mendorong keras lengan Moura. Begitu pula dengan Moura yang tampak tidak senang, sehingga membalas Glend dengan tatapan sinis. Apa maksud dari perkataan Moura barusan? Aneh. Tapi kupikir tidak. Sedari tadi melihat bagaimana cara mereka berdua bersikap, kurasa memang ada yang salah. Aku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku.
***
Perasaanku jadi tidak tenang sejak Glend dan Moura memutuskan pergi dalam keadaan yang canggung dengan alasan hari sudah menjelang malam dan ada suatu hal yang ingin mereka berdua bicarakan. Sempat aku mengatakan bahwa tidak masalah bicara di sini, toh, kami bertiga ini teman. Namun apa daya, dinginnya wajah Glend mengisyaratkan sebuah penolakan dan mereka pun benar pergi. Padahal malam ini aku tidak ingin sendiri, karena di luar sana, pasti ada lelaki itu. Aku tahu dia menunggu di luar. Aku takut. Setidaknya biarlah satu orang yang kukenal menemaniku di sini––Glend, misal––namun kenyataannya aku seperti tidak memiliki siapa-siapa.
Aku ingin mencoba berpikir positif. Jika lelaki itu memang berniat jahat padaku, seharusnya dia langsung saja melakukan aksinya. Tetapi yang kutemukan dari balik kaca pintu kamar, dia justru tampak tertidur pulas di kursi tunggu. Membuatku bertanya-tanya mengenai apa tujuan dia sebenarnya? Menjagaku? Tapi kenapa? Aku tidak kenal dia. Kenapa bukan Glend saja?
Bersamaan dengan itu petir di luar menyambar begitu mengagetkan. Lelaki itu spontan terbangun dan aku langsung bergerak mundur menjauhi pintu. Antisipasi kalau-kalau dia langsung mengintip ke dalam ruang kamarku lagi. Aku pun melangkah menuju jendela kamar dengan niatan ingin menutup gorden. Pantulan wajahku pada jendela yang gelap cukup membuatku berpikir. Seingatku aku memiliki rambut lurus sebahu. Lantas kenapa rambutku sekarang justru panjang dan ikal?
***
Pagi ini aku mendapat bingkisan bunga yang terpajang cantik di atas meja tanpa tahu siapa yang telah memberikannya. Setiap kali kutanya pada beberapa orang suster yang kutemui di lorong, dengan kompaknya mereka menjawab tidak tahu. Berhubung aku sedang tidak ingin pusing memikirkan siapakah pelaku di balik munculnya bingkisan itu, aku memutuskan untuk pergi ke taman. Mumpung dokter memberi izin.
Sesampainya di taman aku duduk di bangku kayu seorang diri, dimana tak lama setelahnya seseorang mendadak muncul di hadapanku.
“Moura?” tanyaku tak percaya, karena ini masih sangat pagi untuk menjenguk. “Ngapain kamu di sini? Sekolah sana.”
Seolah tidak mendengar apa yang kukatakan, Moura justru duduk di sebelahku. Bersender dengan teramat nyaman seakan tak ada lagi beban hidup.
“Gue mau bicara sesuatu.” ujarnya dan aku pun mendengarkan.
“Mau bicara apa?”
“Kita bertiga teman, kan? Oh bahkan lo menganggap Glend lebih dari itu.”
Kepalaku mengangguk pelan. Membenarkan kalimat bagian terakhir.
“Iya, tapi sayangnya aku ngga tau dia anggap aku apa.” kataku mengikuti kata hati. “Kamu masih berpikir dia suka aku?”
Wajah Moura menengadah menatap langit-langit. “Masih.” katanya. “Masih sampai sekarang.” tidak tahu kenapa, tapi nada bicaranya terkesan sedih.
“Apa aku harus bilang duluan?” pikirku.
“Astaga Mia, kenapa sih hal begitu aja mesti terus lo pikirin? Kalau lo yakin, tinggal bilang aja. Emangnya mau lo pendam sampai kapan? Sampai kita bertiga pisah––ngga pernah ketemu lagi––dan akhirnya lo menyesal?”
“Kok ngomongnya gitu sih?” tanyaku agak meninggi.
“Seingat gue, lo pernah bilang kalau kita bertiga ngga bakal bisa dipisahin sama apapun. Apa lo masih yakin sama hal itu?”
Jujur aku paham dengan apa yang Moura tanyakan, justru yang tidak kupahami adalah kenapa dia bertanya hal semacam itu? Beruntung matahari sedang tidak terlalu menyengat, bisa-bisa kepalaku kembali pusing akibat tiba-tiba dihadapi dengan pembicaraan yang di luar dugaan.
“Ra, ada apa sih? Masih masalah kemarin, ya? Aku––” mulutku terkatup saat Moura dengan cekatan mencengkeram kedua bahuku.
“Dengar gue. Jangan pernah berpikir bahwa ngga bakal ada yang bisa pisahin kita. Lebih-lebih jangan pernah berpikir bahwa ngga bakal ada yang bisa pisahin lo dan Glend. Gue tau betul lo suka dia, tapi jangan pernah sekali pun berpikir begitu.” jelasnya lebih serius. Kata demi kata terdengar tegas dengan suara yang sedikit bergetar. Moura masih melihatku lekat-lekat. Kupikir dia akan menangis. Aku bisa melihat jelas jika matanya mulai berkaca-kaca dan hidungnya mulai memerah.
Aku berpikir sejenak. “Moura kamu––”
“Karena Tuhan bisa, Mia. Tuhan bisa.”
Moura menarik mundur posisi duduknya. Melepas cengkeraman tangannya, sementara aku masih diam terpaku tanpa tahu respon seperti apa yang mesti diberikan.
“Apapun yang terjadi, lo harus terima dan kuat menghadapi semua kenyataan yang ada. Buang jauh ungkapan sombong tentang kita––kalian berdua––yang ngga bakal bisa dipisahkan. Ingat itu. Janji sama gue.”
Jari kelingkingnya yang agak pucat sudah mengacung, namun otakku masih berproses dalam tahap mengartikan kata demi kata yang diucap oleh Moura. Sungguh aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Perempuan di sampingku ini terlihat seperti bukan Moura yang kukenal. Dia terlihat berbeda.
“Ayo janji, Mia. Gue ngga ada waktu lagi. Gue harus pergi.”
Merasa tidak ingin mempersulit Moura jika terlambat sampai di sekolah, aku pun mengaitkan jari kelingkingku padanya. Rasanya seperti menyentuh gumpalan kapas.
“Aku janji, tapi––”
Tanpa basa-basi Moura memelukku. Erat, namun tetap terasa ringan. Lebih lembut dari sekedar tersapu angin ataupun tersentuh kapas. Ini pasti mimpi. Biasanya banyak hal aneh terjadi di dalam mimpi.
***
Suhu badanku tiba-tiba saja meningkat. Dalam mata yang tertutup, sayup-sayup kudengar dokter mengatakan kalau ini adalah efek angin luar, sementara suster berpendapat jika mungkin aku terlalu banyak pikiran. Ya. Pendapat yang satu itu bisa kuterima.
Di sela-sela tingkat kesadaran yang belum mencapai seratus persen, telingaku juga ikut menangkap jenis suara yang asing––jenis suara yang belum pernah kudengar. Suara lelaki. Baik dari bentuk pertanyaan juga nada bicaranya, dia tampak sangat khawatir. Bukan ayah, bukan pula Glend. Dan naasnya sosok yang justru terbayang saat mataku terpejam adalah dia.
Sontak aku terbangun dan menjerit entah seberapa kencang hingga seseorang mendekatiku. Dia adalah lelaki asing itu. Melihatnya dalam jarak yang begitu dekat, membuatku tambah menjerit, melempar apapun yang ada di sekitar, hingga besi penyangga infus sempat menjadi sasaran.
Suster pun berupaya menenangkanku––bersama dengan lelaki itu. Sebenarnya mereka bekerja sama ingin bertindak jahat padaku, atau apa? Yang aku rasakan setelahnya adalah tubuhku perlahan menjadi lemas. Mendadak kehilangan tenaga bertepatan dengan suster yang menyuntikkan suatu cairan ke dalam tubuhku. Perlahan mataku pun akhirnya terpejam.
***
Sekarang aku pasti berhalusinasi.
Aku sedang berjalan di suatu tempat dengan latar belakang sebuah gedung besar. Di sebelah kiriku, aku melihat tulisan beserta sebuah logo besar yang berhiaskan air mancur. Anehnya aku tidak bisa tahu tulisan apa itu. Kemudian beberapa orang perempuan berpenampilan dewasa datang merangkulku dari arah belakang. Hingga langkah kakiku mengarah ke pinggir trotoar, kemudian aku terus berjalan mengarah pada salah satu mobil yang terparkir. Saat itu aku merasa adanya hawa seseorang mendekat. Terus mendekat dan kupikir aku memeluknya. Tersenyum, tertawa. Begitu bahagia. Lalu tak lama setelanya aku terbangun.
Tak terasa hari sudah menjelang sore.
“Apa Moura datang?” tanya Glend yang sudah duduk di samping tempat tidurku. Tidak disangka bangun-bangun sudah melihat Glend di sini.
Aku pun mengubah posisi menjadi duduk. Masih agak lemas. “Iya, tadi pagi.”
“Bicara sesuatu?” tanyanya lagi sambil menggeser piring berisi potongan buah apel di atas meja. “Makan ini. Udah dipotongin.”
Seketika aku tersenyum karena akhirnya mendapatkan kembali perhatian dari seorang Glend.
“Moura bicara hal yang ngga aku paham. Ngga paham kenapa bisa-bisanya dia bahas itu padahal masih pagi. Apa ngga bisa dia bahas soal anak-anak di dalam kelas, gimana hasil pertandingan ekskulnya ….” kataku sambil mengunyah sepotong apel. Rasanya setengah manis setengah asam. Membuatku bertanya-tanya dalam hati sudah berapa lama Glend ada di sini? Menungguku bangun dari tidur.
“Emangnya dia bahas apa?”
Aku berusaha menelan gigitan terakhir. Aku tidak mungkin bilang kalau kami berdua juga membahas tentang perasaanku pada Glend yang sampai sekarang masih kusembunyikan. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang dikatakan Moura ada benarnya. Mau sampai kapan aku diam memendam rasa sukaku? Sementara di kenyataannya aku tidak suka jika ada perempuan lain yang juga suka pada Glend. Dan tidak pernah terbayang, entah bagaimana rasanya jika akhirnya Glend ikut membalas perasaan para perempuan itu––bukannya aku.
“Mia?” panggil Glend membuyarkan lamunanku.
“Umm soal perpisahan?” ujarku tak yakin. “Maksudku bukan perpisahan sekolah, tapi semacam perpisahan …. Glend, aku sendiri juga ngga tau apa. Aku bingung. Moura minta supaya aku jangan pernah berpikir bahwa ngga bakal ada yang pisahin kita bertiga. Aneh, kan?” lanjutku mengunyah potongan buah apel yang kedua.
Glend berubah diam. Faktanya dia memang tipe laki-laki yang tidak banyak bicara, hanya saja aku merasa kalau diamnya kali ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang dia pikirkan, tetapi dia tidak mau memberitahuku.
“Karena Tuhan bisa. Pada akhirnya itu yang dia bilang.” timpalku kemudian dan langsung mendapati perubahan raut wajah yang ada pada Glend. “Tuhan bisa pisahin kita. Kamu tau apa maksudnya? Apa kamu juga tau alasan kenapa Moura tiba-tiba bicara begitu?”
Sempat tadinya aku menebak apa mungkin di sekolah baru saja ada ulangan Matematika, Fisika atau Kimia––karena mungkin saja Moura stres karena itu––hingga bicaranya jadi agak melantur, namun ternyata Glend justru tersenyum.
“Kalaupun benar begitu, gue ngga takut.” jelasnya. “Karena mau dipisahin di sini pun, saat ini juga, gue tau kalau lo ngga bakal bisa lupain gue. Apa gue salah?”
Hanya ada dua jawaban yang bisa kuberikan––ya atau tidak. Kupikir ini adalah kesempatanku untuk bilang apa adanya. Aku tidak mau menunggu dan memendamnya lagi, sebelum benar-benar terlambat.
“Ngga.”
Glend melebarkan senyumnya. Kelihatannya dia senang dengan jawabanku. Kalau orang lain tahu bahwa aku lah orang yang menyatakan perasaan lebih dulu, mungkin mereka akan mengatakan kalau aku perempuan yang tidak punya gengsi atau semacamnya. Tapi maaf saja, sama seperti Glend––aku tidak takut.
“Glend sebenarnya selama ini aku––”
“Cukup.” sergahnya memotong. “Gue tau kok, jadi lo ngga perlu bilang. Kok gue bisa tau? Karena perasaan yang sesungguhnya justru lebih bisa dilihat dari perbuatan, bukan dari kata-kata dan lo hampir selalu menunjukkan itu.”
Untuk saat ini aku cuma bisa mendengar dan menatapnya lekat-lekat, sebab aku kehabisan kata-kata juga mati langkah.
“Dan yang terpenting adalah karena emang biasanya bukan perempuan duluan yang bilang. Jadi, maaf kalau ucapan lo tadi gue potong.” lanjutnya dan kami berdua tertawa. “Gue suka lo, Mia. Lo ngga perlu tau apa alasannya, karena terkadang menyukai seseorang itu ngga perlu alasan. Lo juga ngga perlu tau dari kapan, karena yang perlu lo tau adalah sampai kapanpun. ”
Pipiku panas. Saat ini kosakataku seolah hilang begitu saja, sehingga aku tidak bisa menemukan kata demi kata untuk dirangkai menjadi kalimat balasan. Bibirku kaku membentuk lekukan senyuman yang sangat dalam nan lebar dan sulit untuk mengembalikannya ke posisi semula. Rupa-rupanya aku belum siap menghadapi situasi ini.
“Kalau gitu, apa lo mau ikut gue?”
“Ikut? Ke mana?” tanyaku bingung.
“Supaya kita bisa sama-sama terus.”
Aku berpikir. Dia tidak serius mengajakku ke tahap yang lebih serius, kan? Kami berdua masih sekolah.
“Glend, aku cukup kok ketemu sama kamu di sini juga di sekolah.” kataku dengan dibumbuhi sedikit tawa. Sayangnya Glend tidak menanggapinya dengan tawa yang serupa. Dia justru terlihat yakin, seakan mengisyaratkan kalau yang barusan dia katakan bukanlah sekadar candaan.
Hampir saja aku menarik tanganku saat Glend berupaya menyentuhnya, sebab kulit tangannya dingin. Benar-benar dingin. Apa dia terlalu gugup untuk mengakui perasaannya? Lucu sekali.
“Masalahnya adalah gue ngga bakal ada di keduanya dalam waktu lama. Tempat gue udah bukan di sini lagi, Mia.”
Butuh waktu berpuluh-puluh detik sampai akhinya aku membalas, “Maksudnya?”
Aku sadar kalau Glend baru saja menarik napas panjang.
“Yakin mau diperjelas?” tanyanya dan entah mengapa degup jantungku berangsur menjadi lebih cepat. Antara ingin tahu dan tidak ingin tahu, tapi kurasa apa yang akan kudengar bukanlah hal yang baik. Kurasa apa yang ingin Glend jelaskan adalah menyangkut jawaban atas tingkah aneh dirinya juga Moura sejak kemarin.
“Menurut kamu tahun berapa sekarang?”
Spontan aku tertawa. “Apa sih pertanyaan kamu kok––”
“Jawab.” katanya tegas. Tidak ada bercanda-bercandanya sama sekali.
“Iya iya maaf. Sekarang ini tahun 2013. Minggu lalu kan aku baru ulang tahun ke-16. Ngga mungkin aku salah, Glend.” ujarku santai.
“Tapi kenyataannya lo salah.”
Aku diam sejenak. “Salah di mana?”
Seketika pandanganku langsung beralih pada situasi di sekitar. Kepalaku bolak-balik berputar mengitari seisi ruangan. Panik, karena detik ini juga aku baru sadar kalau aku tidak menemukannya. Satu buah pun.
“Apa yang lagi lo cari? Kalendar? Cermin? Majalah? Koran? Handphone?” setiap kali Glend menyebutkan, aku semakin panik. “Baru sadar kalau semua itu ngga ada? Semua hal yang dianggap sebagai petunjuk waktu dijauhkan dari lo, Mia. Supaya lo ngga semakin sakit akibat tiba-tiba tau kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan kalau sekarang ini bukan lagi di tahun yang lo tau. Kalau sekarang ini umur lo bukan lagi 16 tahun.”
Telingaku mendadak berdengung. Pikiranku buyar. Berantakan. Sekelibat bayangan dalam halusinasiku kembali bermunculan. Sesosok lelaki yang kupeluk erat, beberapa perempuan yang kemudian merangkulku, diriku sendiri yang tampak dewasa, ayah, ibu, dan dua buah mobil yang saling berbenturan ….
Tidak ada Moura dan Glend. Tidak ada satupun bayangan dari mereka yang hadir.
“Tapi hal itu ngga berpengaruh apapun buat gue, karena sebelum lo benar-benar ingat, gue yakin kalau lo akan lebih memilih untuk ikut gue.”
Bahuku mengelak saat tangan Glend berupaya menggapainya.
“Mia, lo sendiri yang datang ke masa ini. Lo sendiri yang panggil gue dan Moura. Entah apa alasannya. Mungkin karena lo ngga mau kita pisah, atau karena lo terlalu kangen sama gue dan Moura, atau mungkin juga karena lo belum sempat bilang yang sebenarnya soal apa yang lo rasa––ke gue. Masih ada yang mengganjal di hati lo, Mia, dan itu udah berlangsung enam tahun lamanya. Lantas sekarang saat kesempatan ini datang, apa lo mau buang begitu aja?”
Sungguh aku tidak mau mendengarnya lagi.
“Glend, cukup.”
“Sebelumnya Tuhan memang udah pisahin kita, tapi kita bisa perbaiki. Lo suka gue, begitupun sebaliknya. Kalau lo mau, kita bisa sama-sama terus.” jelasnya berusaha meyakinkanku. “Ayo ikut––”
Tanpa diduga Glend seketika terdorong. Meluncur kencang hingga punggungnya menubruk tembok. Mendapati hal semacam itu terjadi tepat di depan mataku, aku menjerit sekuat tenaga tanpa tahu sebelumnya bahwa jeritanku ternyata sia-sia. Glend yang kupikir akan merasa kesakitan, dia justru lenyap.
Aku hanya ternganga tak percaya.
“Moura?” tanyaku lirih saat menemukan dirinya tengah berdiri di sampingku. Rasa dingin dan lembut ketika jemarinya menyentuh tanganku, tak lagi membuatku terkejut. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya.
Air mataku tiba-tiba mengalir mengiringi hasil pemikiran yang mulai terangkai jelas di dalam kepala. Terlebih lagi saat menemukan kenyataan dimana wajah Moura yang ingin kusentuh, justru tak bisa kugapai. Hanya merupakan sekumpulan udara dingin yang semakin lama semakin memudar.
***
Hidupku menjadi tidak jelas dalam sekejap. Tanyakan padaku pertanyaan apapun, aku yakin bisa menjawab semua, kecuali satu––apa yang sebenarnya terjadi padaku? Baru saja aku merasa menjadi perempuan yang paling bahagia ketika Glend akhirnya menyatakan perasaannya padaku. Namun saat itu juga kebahagiaan itu hilang. Hilang seperti sosoknya yang lenyap begitu saja tepat di depan mataku.
“Diminum dulu.” ujarnya memberikan segelas air mineral padaku. “Mia, kamu harus minum. Harus makan. Ngga masalah kalau kamu masih anggap aku orang asing. Anggap aja aku teman dekat yang datang enam tahun lebih awal.”
Dia, lelaki asing ini memperkenalkan dirinya bernama Jamie. Seorang lelaki yang sebenarnya memiliki posisi yang teramat dekat denganku, namun aku tidak bisa mengingatnya akibat dari kecelakaan mobil yang menimpaku beberapa hari lalu. Jamie menjelaskan bahwa kepalaku mengalami benturan yang agak parah sehingga menyebabkan ingatanku bergerak jauh ke belakang, tepatnya masa-masa di saat aku berumur enam belas tahun. Sementara ayah dan ibu harus pergi merawat nenek yang jatuh sakit ketika mendengar cucu satu-satunya mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, mereka berdua mempercayakan keadaanku sepenuhnya pada Jamie. Membuatnya selalu ada untuk menunggu sekaligus menjagaku di sini setiap waktu. Pantas saja dia selalu ada di depan sana. Merengut setiap kali menemukanku berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Rupanya selama ini aku lah yang menyeramkan, bukan dia.
Lantas kalau sudah begini apa yang harus kuperbuat? Keputusan apa yang harus kupilih? Ikut dengan Glend atau tetap berada di sini––di masa yang belum bisa kuingat dan kuterima sepenuhnya. Hingga akhirnya pada pukul sepuluh malam aku terbangun. Mendapati diriku sendirian di dalam kamar. Dan seperti terpanggil, kedua mataku bergerak mengarah pada sebuah pisau buah di atas meja.
Benar dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Glend. Aku yang menyebabkan hal ini terjadi. Aku yang membuat diriku sendiri mengalami kecelakaan. Aku sendiri yang datang ke masa ini hanya karena aku yang belum rela kehilangan mereka berdua––terutama Glend, lelaki yang sosoknya masih menggantung di hatiku. Dan memang benar kalau aku sangat merindukan dia.
Jadi, biar aku yang menyelesaikannya.
“Ayo potong jari kelingking lo.” ucap Moura entah muncul dari mana. Sementara pisau buah itu sudah berada tepat di pergelangan tanganku. “Bukan untuk mati. Tapi untuk lo sadar, kalau lo ngga menepati janji. Apapun yang terjadi, lo harus terima dan kuat dalam menghadapi semua kenyataan yang ada. Itu janji lo sama gue.” jelas Moura berupaya meruntuhkan niatku.
“Itu artinya, mau atas nama pertemanan kita, rasa suka, sayang, atau apapun, lo tetap harus terima takdir kalau di antara kita bertiga cuma lo yang masih hidup, Mia.”
Aku ingat.
Aku ingat kenangan pahit yang teramat menyedihkan yang dengan terpaksa sekarang ini kurasakan lagi. Betapa sedihnya aku saat itu, ketika tahu Moura dan Glend mengalami kecelakaan setahun setelahnya. Apa daya, mereka berdua tidak selamat. Sungguh aku tidak menerima kenyataan itu dan yang kulakukan hanya menangis serta terus-menerus menyalahkan diri sendiri.
Kurasa aku sudah menemukan jawaban atas kejanggalan yang kutemui pada mereka beberapa hari ini. Kini aku ingat dan yakin. Mereka berdua memang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini.
Tangan Moura perlahan bergerak merangkul kedua bahuku.
“Jadi, tolong, jangan pernah lo berpikir untuk pergi menyusul gue dan Glend. Sekalipun jangan pernah.”
Sakit. Hatiku sakit. Bahkan aku sampai tak mampu bicara sepatah kata pun. Pisau dalam genggaman yang akhirnya jatuh di atas lantai––berdentang nyaring––dan aku hanya bisa menampung air mata dengan kedua tangan. Bersamaan dengan itu pula, sesosok tangan lain menggenggam erat kedua tanganku, menangkupnya walau dingin. Aku masih bisa mencium aroma parfum milik Glend yang selalu dia pakai saat usai bermain basket.
“Mia, gue minta maaf.”
Tak ada yang bisa kulakukan selain menangis sesenggukan.
“Gue cuma mau lo tau gimana perasaan gue yang sebenarnya. Gue menyesal kenapa hal itu ngga pernah tersampaikan. Jadi, di kesempatan ini gue berpikir mau gimana pun caranya, gue mau supaya apa yang direnggut dari gue––yang seharusnya bisa gue dapat––bisa gue ambil balik. Tapi sekarang gue sadar kalau gue terlalu egois. Moura selalu coba menahan niat buruk gue yang terus-menerus mengajak lo ikut, tapi emang gue yang keras kepala. Gue kangen sama lo, Mia. Sangat kangen.” ujar Glend dan aku tak mampu lagi terus-menerus berupaya menahan air mata.
Moura melepas pelukannya. Berganti mengusap air mataku dengan kedua ibu jarinya.
“Lo berhak menjalani hidup lo yang sekarang. Jangan pernah lagi di sia-siakan, ya?”
Glend melepas tanganku dan berdiri mendekati Moura.
“Makasih karena lo udah izinin gue dan Moura untuk datang ke sini lagi. Makasih juga karena lo udah pernah menyukai gue dan akhirnya gue bisa jauh lebih tenang dengan pengakuan itu. Pesan gue cuma satu. Jangan pernah lupain keberadaan gue dan Moura ya, meskipun gue tau lo ngga akan pernah begitu.”
Kepalaku mengangguk pelan. Masih belum mampu bicara.
Untuk yang terakhir kalinya, Moura dan Glend tersenyum dengan wajah yang bersinar. Lalu mereka berdua melangkah bersama menuju pintu. Melihat kepergian mereka, aku hanya memejamkan mata.
Tak lama setelah itu Jamie datang. Duduk di samping tempat tidur, menemaniku yang sudah kembali berbaring. Dia tidak bertanya kenapa aku menangis. Dia justru membisikkan satu hal––besok dia akan mengajakku untuk berkunjung ke pemakaman Moura dan Glend. Entah dia tahu dari mana soal mereka berdua. Apa mungkin beberapa ini dia memperhatikanku yang hampir selalu menyebut nama Glend dan Moura. Entahlah. Setidaknya aku senang karena Jamie memahamiku.
Memang benar. Hati tidak bisa berbohong kalau aku sangat merindukan Glend juga Moura. Hati juga tidak bisa berbohong kalau aku masih memiliki perasaan untuk Glend yang tersimpan baik di sana. Lalu Jamie datang menghadirkan perasaan baru untukku. Sementara aku harusnya tahu bahwa hati tidak bisa menerima dua perasaan sekaligus. Hingga akhirnya aku memilih untuk melepas perasaan yang tersimpan itu dan menggantikannya dengan perasaan yang baru.
Kurasa tetap ada tujuan yang baik dari kejadian ini. Aku akhirnya dengan rela melepas Glend––yang memang pada dasarnya tidak bisa lagi dipertahankan––dan berusaha menerima Jamie seutuhnya di dalam hati.
*** The End ***


 tlotr
tlotr