“Pasien kita Ibu Karsinem, kamar 10, bed 12. Kamu udah liat statusnya?” Dokter Yusuf berjalan dengan cepat di depan Riana. Kepala Dokter Yusuf sedikit menoleh ke kanan sebagai wujud belas kasihannya sehingga Riana dapat mendengar pertanyaan pertamanya pagi itu.
Riana berjalan tergopoh-gopoh di belakang residen[1] tahun pertama itu, jas snellinya[2] yang panjang hingga selutut ikut berkibar-kibar membuatnya agak gusar. Di rumah sakit, berjalan pun ada seni dan peraturannya.
Peraturan pertama, tentu saja, jangan berjalan terlalu lambat karena pasti akan tertinggal jauh.
Peraturan kedua, ah.. nanti saja. Riana harus fokus untuk berjalan lebih cepat sekarang.
Riana mengangguk. Sejenak kemudian tersadar bahwa anggukannya tidak dapat dilihat oleh Dokter Yusuf sehingga ia menggumam pelan, “Sudah, dokter.”
Karsinem (P). 69 th. PN[3] VII (S) et XII (S) ec susp stroke iskemik onset H3. Riana berusaha mengulang apa yang dibacanya sekilas di nurse station tadi dalam hati.
Riana tidak yakin Dokter Yusuf dapat mendengarnya dengan jelas karena seniornya itu sudah berbelok untuk masuk ke ruangan yang ada di depannya. Riana buru-buru menyusul masuk ke ruangan itu. Menghela nafas dalam, ia melirik jam di tangan kirinya: 5.25 dan hari yang panjang sudah dimulai.
“Selamat pagi, Ibu Karsinem. Gimana kabarnya pagi ini? Tidur nyenyak?” Dokter Yusuf menyapa pasiennya dengan riang dan ramah, serta merta disambut dengan senyum lebar Bu Karsinem yang tampak tidak simetris antara kanan dan kiri.
“Ada parese nervus[4] berapa, dik?” Dokter Yusuf bertanya tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengangkat lengan Bu Karsinem untuk memeriksa trofi dan kekuatan otot-otot pasien.
“Parese nervus tujuh, dokter.” Riana menjawab kalem. Padahal dalam hati dirinya berdoa agar jawabannya benar. Setidaknya itu yang dia ingat dari pelajarannya saat S1 dulu.
“Coba Ibu sekarang julurkan lidahnya ya,” Dokter Yusuf memberikan instruksi.
“Kalau ini parese nervus berapa?”
“Dua belas, dokter.” Riana kembali menjawab dengan kalem.
“Yakin?”
“Ya… yakin.” Riana mulai ragu akan jawabannya sendiri. Lidah pasien condong ke kanan, yang berarti… masih terdapat parese nervus dua belas kan?
Atau paresenya sudah tidak ada?
Ahh, otaknya sungguh tidak bisa dipercaya di waktu sepagi ini.
Dokter Yusuf tidak bertanya lebih lanjut dan tetap sibuk melakukan pemeriksaan neurologis pada Bu Karsinem, sementara Riana tetap berdiri dengan khidmat di sampingnya, berusaha mengamati setiap gerakan pemeriksaan yang dilakukan Dokter Yusuf. Barangkali ada satu atau dua jenis pemeriksaan yang bisa ditangkap otaknya yang belum sepenuhnya terbangun itu.
“Selamat pagi, Bu Idah. Perkenalkan saya Dokter Nathan yang akan memeriksa Ibu pagi ini..” terdengar sebuah sapaan dari bed yang berada di sisi kanan Bu Karsinem, sapaan yang menyelamatkan Riana dari lamunan singkat yang tidak disadarinya.
Riana melirik jam tangannya, 05.30. Sepertinya dokter-dokter di sini rajin semua. Ada apa dengan hobi mereka mengunjungi pasien di saat matahari bahkan belum benar-benar terjaga?
Riana berusaha mengintip dari celah tirai antara bed Bu Karsinem dengan bed Bu Idah. Hmm, sayang, Riana tidak bisa melihat dengan jelas wajah dokter yang berdiri memunggunginya.
“Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Semoga semakin cepat membaik ya Bu.” Suara Dokter Yusuf yang agak cempreng yang kali ini membuyarkan lamunan singkat Riana.
Tergesa-gesa Riana mengikuti Dokter Yusuf yang sudah berjalan menuju pintu. Tentu saja, tidak lupa Riana berusaha menoleh ke belakang, ke arah bed Bu Idah yang terletak paling jauh dari pintu.
“Siapa namamu tadi?” Tiba-tiba Dokter Yusuf berhenti setelah keluar dari ruangan pasien yang membuat Riana kaget karena dirinya hampir saja menabrak dokter itu. Arghh, kenapa Dokter Yusuf selalu saja membuatnya kaget?
“Eh? Riana, dokter.”
“Oh iya. Ini hari pertama di Saraf?”
Riana mengangguk. Dokter Yusuf memandangnya dengan tatapan yang aneh. Tatapan yang Riana tidak berani pastikan karena dirinya berusaha melihat apapun di wajah Dokter Yusuf selain matanya. Dadanya berdegup kencang, grogi. Dirinya sungguh tidak pandai berbicara dengan dokter-dokter yang baru dikenalnya seperti ini.
“Besok pagi kita ketemu lagi di jam yang sama di sini.”
“Baik, dokter.” Riana menjawab sambil mengangguk dan badannya sedikit membungkuk, gerak tubuh otomatis yang dipelajarinya selama di Rumah Sakit.
Riana berjalan dengan agak gontai balik menuju nurse station. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.30. Nurse station tampak lengang. Sepertinya teman-temannya masih mengikuti residen masing-masing untuk memeriksa pasien. Perawat-perawat pun masih berkeliling untuk mengganti infus atau memberikan obat kepada pasien. Kini hanya ada dirinya dan Dokter Yusuf yang sedang sibuk mengisi rekam medis Bu Karsinem.
Riana membolak-balik buku catatan kasus pasien yang tergeletak di meja panjang nurse station. Menarik. Riana membaca setiap kasus dengan seksama.
OS[5] datang ke RS dengan keluhan nyeri boyok[6] yang dirasakan sejak 3 bulan yang lalu, makin lama nyeri dirasakan semakin memberat dan menjalar hingga…
“Permisi, dik, boleh geser sedikit?” Seseorang menyenggol lengan kanan Riana, berusaha sedikit mendorong Riana ke kiri.
“Oh, maaf, dok.” Riana segera bergeser ke kiri tanpa menoleh, memberi ruang bagi residen itu untuk menulis di meja.
…. hingga kaki kiri, disertai rasa kebas dan kesemutan hingga ke ujung kaki kiri. Riwayat trauma disangkal, riwayat….
“Boleh pinjam pulpennya, dik?”
“Oh, boleh, dokter.” Dengan sigap Riana mencabut satu dari lima buah pulpen hitam di sakunya dan menyerahkannya pada residen yang menulis di sebelah kanannya itu. Agar dapat melihat wajah dokter itu, Riana harus benar-benar menoleh ke kanan dan mendongak, tentu akan membuatnya tampak sedikit tidak sopan.
***
“Terima kasih,” Nathan mengambil pulpen berwarna putih itu dengan tangan sedikit gemetar dan berkeringat dingin, jantungnya jumpalitan antara senang dan grogi. Apa ini mimpi? Atau halusinasi akibat kurang tidur?
Nathan menuliskan hasil follow up pagi terhadap pasiennya pada selembar kertas rekam medis yang masih kosong, berusaha sekuat pikiran untuk tetap fokus dan mengabaikan degupan jantungnya yang semakin lama semakin menyesakkan dada. Juga berusaha mengontrol bibirnya yang terus ingin tersenyum sedari tadi.
Apakah 2 minggu sudah membuat perubahan yang signifikan pada diriku? Apakah aku tambah ganteng sehingga sulit dikenali?
Dan kenapa pula dia cuek seperti itu? Apakah ini bagian dari profesionalitas di tempat kerja?
“Nat! Nathan! Bengong wae!” Seseorang menepuk sekaligus merangkul pundak Nathan. Aroma parfum yang kuat menyeruak, membangunkan setiap sel penghidu di hidung Nathan hingga membuat hidungnya mendadak gatal.
“Eh, pagi Mas Anton.” Nathan hanya menyapa sekenanya, tangannya masih sibuk menyelesaikan kalimat-kalimat yang sempat tertunda tadi.
“Makasih banyak, lho Nat udah bantu mem-follow up pasienku tadi, padahal kamu habis jaga malam. Gimana, aman semalam?”
“Tidur dua jam, Mas.”
“Wah, berarti aman. Gak aman kalau kamu sampai gak tidur. Iya kan? Hahaha!” Anton tergelak. Guncangan tangan kirinya yang masih merangkul pundak Nathan ikut membuat tubuh Nathan terguncang.
“Eh, tapi tumben kamu nawarin bantuan untuk mem-follow up pasienku. Pasti ada maunya nih!”
Nathan tidak menggubris perkataan Anton. Tangannya tetap sibuk menuliskan semua hasil pemeriksaannya. Ia ingin cepat-cepat terlepas dari rangkulan Anton. Kepalanya mulai pening akibat mencium aroma tubuh seniornya yang seperti diguyur 1 liter minyak nyong-nyong ini.
“Kalo kamu minta aku untuk gak bertanya pertanyaan sulit saat kamu presentasi kasus besok… Tenang aja! Karena permintaanmu itu sudah pasti akan terkabul! Hahaha!”
Nathan menggaruk telinganya yang gak gatal sama sekali. Kenapa seniornya ini begitu senang tertawa tepat di sebelah telinganya?
“Soalnya besok aku ada bimbingan dengan Dokter Juni, jadi so pasti aku gak bisa datang ke presentasi kasusmu! Hahahahaha!”
Duh. Lagi-lagi dia tertawa. Nathan merutuk dalam hati. Kalau bukan karena pasien Mas Anton berada di kamar yang sama dengan Bu Karsinem, tentu dirinya tidak akan menawarkan bantuan.
“Bagaimana kondisi Bu Idah? Nanti akan aku kunjungi setelah Poli[7] selesai,” akhirnya ada sedikit keseriusan di suara Anton. Nathan menarik napas dalam. Paling tidak, Anton tidak akan tertawa di telinganya lagi.
Nathan membubuhkan tanda tangannya di lembar rekam medis terakhir yang ditulisnya. Menutup pulpen putih yang digunakannya, Nathan menoleh ke kiri, “Lho? Kemana perginya?”
“Siapa? Daritadi gak ada siapa-siapa di sebelah kirimu.” Anton ikut celingak-celinguk, mencari sosok yang dia pun tidak tahu.
***
5.20.
Riana berjalan menyusuri koridor bangsal Anggrek yang remang-remang. Snelli yang dikenakannya ikut melambai-lambai mengiringi langkahnya yang cepat dan lebar. Dirinya tidak habis pikir kenapa residen pembimbingnya itu begitu rajin. Rasanya semakin hari semakin pagi saja jadwal follow up-nya.
Dengan sigap Dokter Yusuf melakukan pemeriksaan-pemeriksaan fungsi saraf pada Pak Wardoyo, sembari bertanya-tanya beberapa hal kepada Pak Wardoyo dan istrinya yang saat itu menunggui di rumah sakit.
“Coba kamu periksa klonus pasien.” Tiba-tiba saja Dokter Yusuf meminta Riana melakukan pemeriksaan yang belum pernah dipelajari, apalagi dilihatnya sebelumnya.
Dengan gugup Riana mendekati bed pasien, tangannya merogoh saku jasnya, mencari benda yang dapat membantunya. Jujur saja, Riana tidak tahu apakah dirinya perlu menggunakan palu refleks atau tidak. Stetoskop? Haha, tentu tidak perlu. Penlight? Bukan, bukan. Tangan kosong?
Bingung, Jujur adalah pilihan terbaiknya.
“Maaf, dokter, saya belum pernah….”
“PR. Nanti sore kamu perlihatkan ke saya caranya,” potong Dokter Yusuf cepat dengan suara pelan, tanpa menoleh sedikit pun pada Riana.
Riana menarik napas dalam, menghitung 1-2-3 sebelum menghembuskannya kembali. Sungguh Riana benci merasa malu dan bersalah seperti ini.
***
“Sudah kamu baca pemeriksaan-pemeriksaan neurologis yang ada di textbook?” Dokter Yusuf bertanya sambil menekan tutup botol alkohol di dinding dan mencuci tangannya.
“Su.. Sudah, dokter,” jawab Riana pelan. Rasa-rasanya dirinya akan terkena masalah.
“Lalu, kenapa belum tahu pemeriksaan klonus?” Tanya Dokter Yusuf lagi sambil berjalan. Dingin. Susah payah Riana mengikuti langkah Dokter Yusuf, juga berusaha memikirkan alasan yang tepat untuk ketidaktahuannya pagi itu.
Tiba-tiba Dokter Yusuf berhenti. Dengan sigap Riana menarik rem agar tidak menabrak punggungnya. Selalu. Saja. Mengagetkan.
“Nanti sore temui saya di sini pukul 4. Cari pasien untuk melakukan pemeriksaan klonus.”
Tanpa basa-basi lagi, Dokter Yusuf melenggang pergi. Kali ini Riana tidak bersusah payah untuk berusaha mengikuti langkah Dokter Yusuf. Disandarkannya tubuhnya ke dinding koridor yang masih juga tampak remang-remang. Cahaya matahari memang tidak pernah sampai ke koridor itu.
Riana melirik jam tangannya. Kali ini terlalu cepat. Masih pukul 05.30.
Riana menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Awal hari yang agak buruk.
“Ayo ikut aku.” Riana merasakan tepukan di pundaknya. Riana menurunkan tangan yang sedari tadi menutupi wajahnya dan mendapati seorang residen telah berjalan melewati dirinya.
Aku? Aku kah orang yang dimintanya?
Buru-buru Riana menyusul residen yang tampak akan masuk ke sebuah ruangan di depannya.
“Per.. Permisi, dok?”
“Iya, kamu.” Tanpa menoleh residen itu menyahut dan masuk ke kamar nomor 10.
Celingak-celinguk, Riana tidak tahu bagaimana cara menemukan bed mana yang residen tadi kunjungi. Di ruangan itu terdapat 6 bed pasien, semuanya masih dikelilingi tirai hijau. Yang… mana… kah?
“Di sini.” Sebuah suara muncul dari bed paling ujung sisi kanan. Ah, bed 13. Rupanya residen itu tahu bahwa Riana kebingungan.
Riana menyibak tirai yang mengelilingi bed pasien. Didapatinya seorang pasien laki-laki berusia 60 tahunan, dan seorang dokter berdiri di sebelah kanan tempat tidur pasien. Dokter itu tampak berbincang-bincang dengan ramah dan santai, sembari melakukan beberapa pemeriksaan pada tangan dan kaki pasien.
“Waktu itu belum sempat aku tunjukkan. Ini pemeriksaan klonus.” Tanpa aba-aba dokter yang tidak Riana ketahui namanya itu melipat lutut dan telapak kaki pasien sedemikian rupa sehingga muncul gerakan menyentak-nyentak pada kaki pasien.
“Coba kamu lakukan.”
Huh? Waktu itu? Aneh.
Riana mendekati pasien, meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, dan menirukan maneuver seperti yang dicontohkan residen tadi.
“Bagus. Coba sekali lagi.”
Riana mengulangi pemeriksaannya lagi.
“Nathan! Di sini kamu rupanya! Dokter Arfi mencarimu. Kamu ditunggu di ruangan beliau. Cepat!” Seorang dokter perempuan datang tergopoh-gopoh, memanggil dokter yang berada di depan Riana dengan agak berbisik supaya tidak menganggu pasien lain.
Dokter Nathan.
Riana tersenyum kecil. Baik sekali.
***
“Sejak kapan kamu jadi residen pembimbing koas?” Gina berjalan di sisi Nathan, pandangannya menyelidik.
“Kenapa Dokter Arfi memanggilku?”
“Bukannya R5[8] udah gak membimbing koas lagi? Itu kan tugas R1[9]!” Gina masih belum putus asa.
Nathan mendadak berhenti dan menatap Gina bingung. “Dokter Arfi benar-benar memanggilku?”
“Iya, tapi nanti siang, pukul satu!” Jawab Gina ketus.
Aneh. Mengajari koas? Sejak kapan Nathan tertarik lagi?
Nathan menatap Gina dengan heran dan kesal. Kalau begitu, kenapa harus buru-buru memanggilnya keluar seperti ini? Nathan berbalik dan melihat tidak ada tanda-tanda gadis tadi keluar dari kamar nomor 10.
Mungkin aku harus kembali ke sana.
“Jangan balik ke sana. Ayo kita ke ruang ilmiah, sudah pukul tujuh.” Seperti dapat membaca pikirannya, Gina menarik lengan Nathan menjauhi kamar nomor 10.
Sudah dua tahun berlalu dan Gina masih tidak suka Nathan memasuki kamar nomor 10 itu.
***
Riana berjalan mondar-mandir di depan nurse station. Tidak terasa ini minggu keempatnya di bagian Saraf. Sudah saatnya dirinya melaksanakan miniceex[10] bersama residen yang ditunjuk oleh dosen pembimbingnya.
“Kamu ujian sama saya kan? Sudah memilih pasiennya?” Dokter Gina bertanya tanpa sedikit pun keramahan di suaranya.
Nyali Riana langsung ciut.
Apakah ini mendung sebelum badai?
***
“Bukan begitu! Tangan kirimu pegang dahi pasien supaya kepala pasien tidak bergerak!” Dokter Gina membentak Riana yang baru saja memulai rangkaian pemeriksaannya.
Riana membeku sesaat. Kaget, namun cepat-cepat ia berusaha menguasai diri.
“Baik, dokter.” Riana memperbaiki posisi tangannya dan mulai melanjutkan pemeriksaannya lagi.
“Hhh! Kamu udah belajar belum sih?! Sebelum periksa kamu minta pasien ngapain dulu?”
Riana membeku lagi. Berpikir, Riana. Berpikir.
“Maaf, dokter. Seharusnya saya minta pasien menutup mata terlebih dahulu.”
Dokter Gina tidak menyahut. Riana pun melanjutkan.
“Berhenti! Bukan gitu caranya!” Lagi-lagi Dokter Gina membuat Riana kaget dengan komentar ketusnya.
Keringat dingin mulai menetes di dahinya. Snelli yang berbahan tebal ini pun membuat Riana merasa begitu kepanasan dan sesak. Haruskah Dokter Gina terus mengomentarinya dengan ketus di hadapan pasiennya yang sudah renta ini?
Rasanya Riana ingin berhenti dan keluar saja dari kamar pasien itu. Air mata sudah menumpuk di pelupuk matanya.
Semoga ini cepat berakhir. Lulus tidak penting lagi, asalkan penyiksaan berkedok ujian ini segera berakhir.
***
“Gina!” Nathan sedikit berteriak sambil mengejar Gina yang berjalan menuju lift.
“Gina! Tunggu!” Nathan menarik lengan Gina, mencegahnya untuk masuk ke dalam lift yang sudah terbuka.
“Kenapa sih, Nat?” Gina berhenti, wajahnya cemberut.
“Aku yang harusnya bertanya seperti itu!” Nathan melepas lengan Gina yang ditariknya tadi dengan agak kasar. Nada suaranya tinggi, namun bibirnya terkatup rapat. Matanya menatap Gina dengan penuh rasa marah dan kecewa.
Gina memiringkan kepalanya ke kanan, bingung.
Nathan menggamit lengan kanan Gina lagi dan menariknya menuju tangga darurat tepat di sebelah lift.
“Aku lihat, Gin,” ucap Nathan dengan suara yang berusaha didatar-datarkannya.
“Lihat apa sih, Nat? Bicara yang jelas! Ini udah sore, aku mau pulang!” Gina menyenderkan tubuh lelahnya pada tembok.
“Lihat caramu menguji koas tadi. Kamu keterlaluan.” Nathan begitu dingin, membuat Gina sedikit menggigil.
“Aku gak paham apa maksudmu, Nat. Ayo kita pulang.” Gina berjalan menuju pintu tangga darurat. Nathan dengan sigap menghalangi langkahnya.
“Aku mau kamu minta maaf pada koas yang kamu marahi di depan pasien saat ujiannya.” Nathan menatap mata Gina lurus dan dalam. Gina menatap mata Nathan balik. Kemarahan. Gina memalingkan wajahnya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak.
“Kenapa kamu begitu peduli, Nat?”
Nathan diam.
Kenapa kamu selalu begitu peduli pada orang lain selain aku? Lanjut Gina dalam hati.
“Kalau kamu begitu peduli, kenapa tidak menghentikanku tadi?” Tatap Gina, menantang.
Kepedulianmu padanya lah yang membuatku bersikap tidak adil seperti tadi. Maafkan aku.
“Karena aku terlambat. Aku mendengar bentakan-bentakan terakhirmu sebelum kalian mengakhiri ujian itu.”
Gina mendengus. Hening kini menyelimuti keduanya.
“Lantas kenapa kamu di sini sekarang? Kenapa tidak pergi saja temui koas tadi dan hibur dia?”
Nathan menunduk. Posturnya yang sedari tadi tegak dan tegang sekarang tampak lesu.
“Dia sedang bersama Yusuf.”
Gina tertawa singkat, sumbang.
“Riana, ya. Cinta barumu rupanya. Sudah kuduga sejak awal.”
Nathan mendongak. “Riana?”
“Iya. Riana kan nama koas itu? Huh! Seleramu tidak berubah.” Gina mencibir. Kedua tangannya dilipat di depan dada.
“Riana?” Nathan masih membeo. Wajahnya kini tampak sangat bingung. Mata bingungnya menatap Gina, berusaha mencari jawaban.
Seketika Gina membelalak. Dirinya kini menyadari sesuatu. Sesuatu yang selama ini mengusiknya setiap kali melihat Riana. Rasa kesal yang selalu muncul setiap kali melihat gadis itu… Memang mirip! Sangat mirip, tetapi tidak serupa. Kenapa dirinya tidak menyadarinya sejak awal? Air mata mulai mengumpul, siap untuk keluar kapan saja. Hatinya turut sakit untuk Nathan.
“Nathan…”
Nathan masih diam, kali ini tatapannya kosong, lurus ke depan.
“Nat…” Gina mendekat, disentuhnya lengan Nathan yang tertutup jas dokter itu.
“Pantas saja dia tidak mengenaliku..” Lirih, Nathan berbicara lebih kepada dirinya sendiri.
“Nat, Tiara sudah pergi. Dia gak akan kembali. Sadar, Nat, please.”
Nathan seketika lunglai. Dijulurkannya tangan kanannya ke tembok agar tubuhnya tidak seketika ambruk dan berguling di tangga darurat itu. Walau itu hal yang ingin sekali dilakukannya sekarang. Air mata mulai mengaliri pipinya.
Gina mendekati Nathan, memeluk lelaki yang begitu rapuh itu dari samping, berharap dirinya dapat sedikit memberikan kekuatan. Trauma yang dialami Nathan begitu besar, begitu dalam.
***
“Kamar nomor 10, benar?” Nathan berjalan dengan langkah panjang dan hati riang. Follow up pagi kini menjadi momen-momen yang dinantikannya.
“Iya, dokter,” sahut gadis cantik di belakangnya dengan tidak kalah riang. Kuncir kudanya bergoyang seiring dengan langkahnya. Snellinya yang panjang pun ikut melambai senang.
“Selamat pagi, Bapak Joko. Saya Dokter Nathan dan ini Dokter Muda Tiara yang akan memeriksa Bapak hari ini.”
***
“Kamar nomor 10 lagi, benar?” Tidak ada jawaban, Nathan menoleh ke belakang, mendapati Tiara yang jauh tertinggal, sibuk melihat layar handphone-nya untuk mengecek nomor kamar pasien mereka pagi itu.
Nathan berbalik, menggamit lengan Tiara dan berbisik, “Kamar 10 kok, kamar favorit kita, sudah aku cek.”
“Dok…” Tiara berusaha menarik tangannya dari genggaman Nathan. Tapi Nathan malah menggenggamnya makin erat.
“Dok, kalau ada yang lihat…” Tiara melihat ke sekeliling, barangkali ada dokter, perawat atau keluarga pasien yang sedang berkeliaran di koridor.
“Tenang, masih pukul 05.30, terlalu pagi untuk dokter-dokter lain melakukan follow-up.” Nathan tersenyum lebar.
“Makanya jam follow up kita aku majukan, hehe..” Nathan nyengir kuda. Tiara balas tersenyum, malu sekaligus senang.
***
“Tiara! Bangun Tiara! Bangun Tiara! Aku mohon!” Nathan masih menekan dada Tiara dengan sekuat tenaganya, berharap tekananannya cukup kuat untuk membangkitkan jantung Tiara yang sudah menyerah. Jangan menyerah, Tiara… Kamu gak pernah menyerah sebelumnya. Jangan menyerah kali ini, aku mohon…
Nathan memohon dan menangis. Memohon dan terus memompa jantung Tiara. Terus memompa dan menangis, hingga kedua tangannya tidak dapat dirasakannya lagi. Hingga serpihan-serpihan harapan, yang tadi berusaha digenggamnya, lolos dari sela-sela jarinya, untuk selama-lamanya.
***
Gina masih memeluk Nathan yang menangis sesenggukan di pojok tangga darurat yang semakin gelap…
Nathan… cintamu telah pergi di minggu kedua koasnya di sini. Sudah dua tahun, Nat… bukan dua minggu.
[1] Residen: Dokter yang sedang belajar untuk menjadi spesialis
[2] Snelli: jas putih yang dipakai oleh dokter dan dokter muda (koas)
[3] PN = Parese Nervus; kelemahan saraf
[4] Nervus = saraf
[5] OS = pasien
[6] Boyok = pungguh bawah
[7] Poli = poliklinik
[8] R5 = Residen Semester 5
[9] R1 = Residen Semester 1
[10] Miniceex = Ujian yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien


 putuyena
putuyena







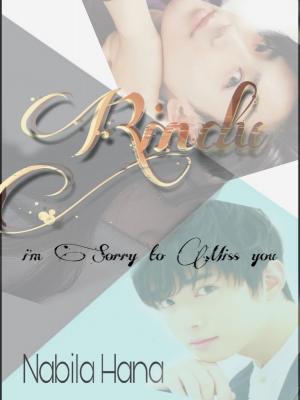


bagus ceritanya, jika berkenan tolong Like ceritaku juga ya https://tinlit.com/read-story/1436/2575
terima kasih , smoga sukses selalu :)