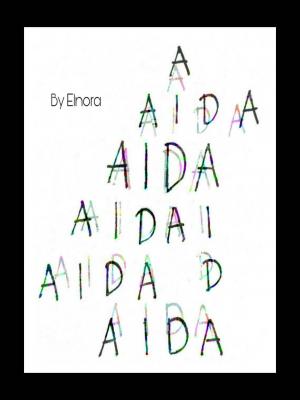“Kalian sudah ngapain saja?” tanyaku super excited. “Kamu mabuk dan berakhir di kamarnya?”
“Apartemennya!” sergah Melly.
“Iya, tapi dia tidur di kamarnya,” Sharon menyanggah balik.
Mitha meneguk lemon teanya yang sudah hampir habis. Dia tidak langsung menjawab. Matanya berputar-putar seperti mencari jawaban. Aku merasa dia seperti menutupi sesuatu, atau mungkin sedang kelimpungan menyusun kata-kata yang tepat. “Kami jalan-jalan seharian. Jadi, hari Sabtu itu kami benar-benar berdua bersama. Mostly hanya mengobrol, kuliner, lalu malamnya kami pergi ke pub di daerah sana. Aku berniat mengorek informasi tentang dia, tapi memang sepertinya dia benar. Dia single.” Mitha berhenti melanjutkan ceritanya dan menunduk melihat ke kedua telapak tangannya. Dia kelihatan gugup. “Ya, aku berakhir tertidur di apartemennya karena mabuk.”
“Kamu yakin dia nggak memberikan obat tidur sewaktu di bar itu? Coba ingat-ingat lagi mungkin kamu ke toilet cukup lama?” Melly curiga.
Mitha menggeleng. “Memang dasar aku yang kebanyakan minum.”
“Lalu apa rencanamu?”
Mitha melihatku dengan tatapan penuh tanya. Seketika aku bisa merasakan perasaannya yang bingung. Aku paham sekali berada di posisinya saat ini. Bingung dan serba salah. Rasanya kau ingin menyalahkan dirimu sendiri karena sudah nekat pergi dengan orang asing, sampai mabuk dan tertidur di apartemennya. Kau tidak tahu apa yang terjadi selama kau mabuk dan tertidur.
“Rencanaku?” Mitha melihat ke arah meja di depan kami. Empat orang wanita muda sedang sibuk mengobrol entah membahas apa. Mereka sesekali tertawa keras sampai seisi café mendengarnya. “Aku belum punya rencana apapun. Let it flow aja seperti air. Lagipula, dia juga tidak berubah sikap atau menunjukkan gerak-gerik aneh.”
“Jadi, ada yang bakal pindah ke Jakarta nih….” Melly bertatap-tatapan melempar kode denganku sambil tersenyum menggoda penuh arti.
“Apaan sih?!” Mitha protes, tapi wajahnya memerah malu.
“Jadi yakin nih nggak ngapa-ngapain lagi?” Melly mencecar Mitha yang sudah merah semerah tomat wajahnya. Dicecar dengan pertanyaan seperti itu semakin membuatnya menjadi tomat matang.
***
Langkahku gontai menyusuri lorong kamar hotel yang sepi. Hanya terdengar suara volume TV dari satu dua kamar hotel, suara orang bercakap-cakap dari dalam kamar, atau suara anak-anak kecil yang masih aktif bermain sambil berceloteh ini itu.
Sesampainya di depan pintu kamarku, aku meng-unlock pintu kamar. Kamar hotel terasa seperti lembap jika ditinggalkan seharian. Secara otomatis jariku menekan tombol lampu di tembok, dan kamar hotel menjadi terang benderang. Kulepaskan sepatu heelsku. Kakiku terasa sangat pegal seperti mau copot. Baru saja memijat-mijat kakiku, handphone di tasku bergetar beberapa kali. Bukan telepon, bukan. Itu getar tanda ada pesan Whatsapp yang masuk. Awalnya kupikir dari Mitha dan Melly yang masih sibuk membahas si sugar daddy-nya Mitha. Ternyata dugaanku salah besar. Mataku terbelalak membaca isi pesan Whatsapp dari nomor yang tak dikenal. Pesannya singkat-singkat, tapi membuatku jadi waspada.
Halo...
Lagi di mana?
Inget gue nggak?
Aku tidak mau tinggal diam. Segera kutelepon nomor tersebut. Nomornya aktif, tapi tidak ada yang mengangkat. Dia mengirimiku chat lagi.
Jangan telpon. WA aja.
Aku mendengus. Baiklah kalau begitu. Aku sudah bisa membaca ke mana scenario ini akan berakhir. Ini pasti tak lain dan tak bukan adalah orang suruhan David.
Jangan bohong. Kamu disuruh David, kan?
Dia tidak membalas, tapi online. Dia curang. Dia mematikan tanda dibacanya. Sial!
Balik ke Jakarta, he kamu gundik. Jangan kabur kamu ya!
Shit! Kugigit bibir bawahku sambil kebingungan. Malas berargumen dengan orang tak jelas, tanpa pikir panjang lagi kublokir nomor tak dikenal itu, lalu kumatikan paket dataku. Aku segera meringkuk di bawah selimut, menyalakan TV dengan volume yang keras, dan tidak mematikan lampu kamar sampai aku terlelap dalam cemas.
***
Aku kesiangan. Semalam tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali aku terbangun. David terus menghantuiku. Sampai sekarang aku tidak berani mengaktifkan paket dataku. Tapi aku tidak bisa terkurung di sini terus. Aku harus keluar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. David akan merasa menang jika mata-matanya melaporkan aku menjadi waspada dan takut. Akhirnya, setelah membulatkan tekad, aku keluar kamar dengan tas gym ku. Sudah jam 8 pagi, dan belum sarapan pula! Dengan sedikit berlari aku menuju ke lift, kutekan tombol angka 5.
Ada beberapa tamu hotel yang sedang menikmati sarapan di sana. Sebenarnya aku tidak terlalu nafsu makan. Chat teror semalam masih terngiang-ngiang di kepalaku. Tidak bisa kupungkiri kalau teror itu memang berhasil membuat pikiranku kalut meskipun aku kini berpura-pura semuanya aman. Aku mengambil meja di pojok, dan hanya makan buah.
Saat sedang menikmati buah, aku tersadar akan sesuatu. Laki-laki yang beberapa hari lalu bertemu denganku di lift. Dia sedang sarapan juga. Sendirian. Tepat duduk di seberangku. Kenapa tadi aku tidak melihatnya? Ah, lupakan… Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia pengusaha. Dia kelihatan sangat sibuk dengan handphone-nya. Jarang sekali dia mengangkat pandangan dari layar kecil itu. Kapan aku bertemu dengannya? Hari apa? Ah… aku lupa. Yang aku ingat, aku di lift dan akan pergi ke tempat gym. Sedang asyik-asyiknya memperhatikan dia dari tempatku, dia mengangkat pandangannya lalu mata kami bertemu. Dia tersenyum padaku. Tindakannya membuatku terpana sesaat sebelum aku memberikan senyum tipisku. Di saat yang sama handphone ku bergetar. Karena terkejut, aku sampai menyenggol cangkir kopiku dan menjatuhkannya ke lantai. Bunyi cangkir keramik yang beradu dengan lantai hotel terdengar sangat nyaring, memenuhi seluruh restoran hotel ini. Panik dan hectic, karyawan hotel membantuku membersihkan pecahan cangkir itu dan aku tak sempat mengangkat telepon yang tadi berdering.
Setelah insiden pecah belah itu selesai, aku kembali ke meja makanku. HP ku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku hanya bisa gigit jari… Ku reject, nomor itu menelpon lagi, ku reject lagi, lagi, dan lagi. Sial, nomor itu tetap menelponku. Keras kepala sekali penerorku ini! Akhirnya aku terpaksa mengangkat telponnya.
“Ha-halo?” kataku lirih, tidak mau sampai kedengaran siapa-siapa.
Tidak tahu sopan santun, teleponku langsung dimatikan dan nomorku diblokir. Aku tidak bisa menelpon balik nomor itu. Apa-apaan ini?
Laki-laki yang duduk di seberangku melihatku dengan tatapan aneh sambil meneguk kopinya.
***
“Kamu di mana, Mel?” tanyaku dengan suara lirih. Aku sudah berada di dalam Mall Ambarukmo Plaza, salah satu mall yang sangat ramai di Yogyakarta, tapi aku masih merasa tidak aman, paranoid. Melly bilang sudah di parkiran motor dan akan segera menyusulku. Sambil harap-harap cemas, aku menunggunya di dekat ATM Center.
“Kak!” Dia memanggilku sambil setengah berlari. Lega sekali rasanya waktu aku melihatnya.
“Kakak nggak apa-apa?” Dia kelihatan khawatir.
“Iya, aku nggak apa-apa. Tapi aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana,” jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. Sejujurnya aku masih syok dengan terror yang kuhadapi ini. Aku merasa diriku amat sangat terancam.
Melly memegang kedua tanganku. “Kak, tangan kakak dingin banget. Kakak nginep kos aku dulu aja, ya? Ada aku, kok. Atau kakak mau nginep di apartemen aku sama Bryan? Bryan pasti nggak keberatan, kak. Malah aman kalau ada cowoknya. Kakak tenang aja. Nanti kakak bisa pinjam baju aku. Beli sekarang di sini juga bisa. Ok?”
Tawarannya menggiurkan, tapi aku tidak mau Melly sampai terseret karena aku. Aku tidak mau keselamatannya terancam hanya karena aku. Dengan terpaksa, aku pun menolaknya. “Mel, thank you banget buat tawaran kamu. I really appreciate that, tapi percaya deh sama aku, aku baik-baik aja, kok. Sekarang memang aku syok, tapi aku yakin besok aku udah better. Aku cuma mau minta tolong kamu buat temani aku seharian ini. Kamu nggak apa-apa, kan?”
Melly mengangguk. “Aku free, kok. Kakak tenang aja. Yang penting ada yang temani kakak. Jangan sampai ada sesuatu.” Aku bisa melihat ketulusannya dari sorot matanya yang semakin membuatku tidak tega merepotkannya, apalagi jika sampai harus melibatkan dia dan terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku kalau sampai orang-orang tak berdosa di sampingku harus ikut menjadi korban.
“Kakak mau jalan-jalan? Atau mau makan? Yuk, kita beli gelato?”
Aku mengangguk. “Aku traktir kamu. Ok? Nggak boleh nolak.”
Dia terkekeh sambil menggeleng. “Oke, oke. Tapi kakak janji, kan? Kalau ada apa-apa, kakak langsung ke apartemen aku aja. Kakak bisa ke kos Mitha. Oke, kak?”
Aku hanya bisa menatap wajahnya, namun tak bisa mendeskripsikan artinya. Dia mengkhawatirkan kondisiku. Bibirnya mengatup-atup seperti seekor ikan. Sementara aku hanya pasrah dengan semesta.


 Vprames
Vprames