April, 2001
Suara teriakan-teriakan itu menjerit di balik pintu. Pekikan, hinaan, decit ketakutan. Membaur bersama sakitnya tamparan dan pecahan benda berkaca. Mungkin meja rias di dalam sana telah hancur dengan hantaman kursi.
“Istri nggak berguna!”
Dan aku hanya bisa menutup kedua daun telinga dengan erat. Mendekapkan badan lebih dalam di balik selimut. Mencoba sekuat mungkin untuk tidak menangis saat membayangkan kondisi perempuan yang amat berharga untukku. Ibu.
“Nggak berguna!”
Bibirku menipis. Gigi atas menahannya dengan gigitan geram. Sialan. Sialan. Aku sungguh membenci suara itu. Sebenarnya siapa yang tidak berguna? Laki-laki yang kerjanya hanya tahu meja biliar dan perjudian tahu apa tentang hal yang berguna dan tidak?
“Cukup, Pak. Nanti di dengar Yuli.”
Kali ini napasku tertahan mendengar paraunya suara itu. Ibuku yang malang tengah memohon pada orang yang tidak pantas untuk dimintai permohonan. Lagipula tentu saja setiap malam aku mendengar suara teriakan yang menyayat hati ini, bahkan para tetangga mungkin diam-diam ikut mengutuk pembuat onar di tengah lelapnya tidur mereka. Jika kekerasan yang diciptakan itu tak bersuara pun, keesokan harinya aku akan tetap tahu dengan munculnya memar baru yang menempel di kulit ibu.
Kenapa ada laki-laki di dunia ini? Kenapa harus ada pernikahan jika hanya untuk pelampiasan emosional? Kenapa? Sungguh, aku berjanji tidak akan menikah. Dengan siapa pun. Selamanya. Hingga liang lahat memeluk tubuhku.
Pernikahan adalah hal yang paling memuakkan.
***
“Yuli!”
Seseorang menepuk punggungku keras. Berusaha mengejutkan, tapi bagaimana bisa aku terkejut jika aku sudah hafal dengan rutinitasnya ini?
“Matamu kenapa?”
Dan pertanyaan itu pun seakan-akan sudah menjadi kewajiban untuk dilontarkan.
“Kemarin Bapak sama Ibu…” Aku tidak perlu melanjutkan ucapanku saat Dini sudah memelukku dengan cepat. Dia mengerti. Tentu saja.
Pelukan yang menenangkan ini pun juga telah menjadi kebiasaan. Pelukan yang bisa membuat rasa sesak di dadaku sedikit berkurang; bahwa di dunia ini tidak hanya ada kekerasan tapi juga kelembutan.
“Oh ya, buruan ke kelas! Aku belum ngerjain PR Bahasa Indonesia! Aku nyalin punyamu, ya!”
Tarikan tangan setelah pelukan yang menenangkan itu juga menjadi hal rutin untukku. Dini yang mampu memberiku sandaran juga keceriaannya. Lihatlah bagaimana dia menyeruak sekurumun siswa di lorong sekolah dengan terus menarik tanganku. Di saat ini, aku berperan sebagai orang yang terus mengucap maaf pada setiap orang yang menjadi “korban tabrak lari” Dini.
“Aduh, maaf!”
Kali ini kecepatan lari Dini benar-benar seperti lomba lari marathon. Tanganku bahkan telah lepas dari tarikannya karena tubuhku yang bertabrakan cukup keras dengan seorang siswa. Beruntung aku masih bisa menjaga keseimbangan, walau aku dan si korban sama-sama terpental.
“Gawat! 5 menit lagi udah masuk!” teriak Dini dengan terus berlari. Tanpa menoleh ke belakang.
“Kamu nggak apa-apa?” Siswa yang menjadi korban lari kesekian bertanya padaku yang masih mendengus sebal menatap Dini.
“Nggak apa-apa kok. Maafin temenku, ya.”
Aku kembali membuat langkah lebar-lebar setelah mendapat anggukan dari siswa itu. Dasar Dini. Rasanya seluruh siswa di SMA ini akan hafal dengan wajahku dan wajah Dini karena selalu membuat keributan di koridor.
“Yuli, kamu nulis puisi untukku, kan?” tanya Dini dengan raut muka cemas. Aku mengangguk. Mengeluarkan buku catatan dan langsung di ambil dengan cepat oleh Dini.
Senyumnya sudah melebar sempurna. Mungkin kekhawatirannya untuk di hukum di depan kelas telah menghilang karena tidak mengerjakan tugas. Namun senyum itu seketika menghilang saat membaca judul puisi.
“Darah hitam.”
Dini langsung menatap tajam padaku yang sudah ambil duduk di sebelahnya. Aku hanya bisa menggidikkan bahu.
“Sudah kubilang buatin puisi cinta. Tentang perasaan. Bukan yang horor begini,” gerutu Dini.
Aku membantah, “Itu puisi cinta.”
“Kamu bilang cinta, dulunya. Kamu menjagaku, dulunya. Kamu membenciku, nyatanya. Kamu menyakitiku, nyatanya. Menebar racun pada tinta merah di dada. Berdendang bahwa perasaan itu telah kadaluarsa. Simbol merah yang menyatukan kita telah ternoda. Menghitam. Kelam. Menghilang.”
“Gimana? Bagus, kan?” tanyaku. Dini menghela napas panjang. Masih dengan mengerucutkan bibir menyalin puisi dengan tidak rela. Ekspresi wajahnya ini membuatku tertawa. Dia pasti kesal setengah mati karena puisi ini, tapi mau tak mau harus tetap menulisnya demi tidak mendapat teguran Pak Dayat.
“Kamu harus jatuh cinta biar bisa nulis puisi yang bahagia, Yul,” gumam Dini. Aku menggeleng.
“Aku nggak perlu.”
“Perlu. Nantinya kamu juga pasti akan menemukan laki-laki itu.” Dini masih kekeh.
“Nggak akan.” Aku pun juga tidak mau kalah.
“Akan! Memangnya kamu nanti nggak menikah?!” seru Dini.
“Memang,” ucapku, tenang dan meyakinkan. Dini sudah melongo. Menggeleng-gelengkan kepalanya tak habis pikir.
Bibirnya kembali terbuka. Ingin membalas ucapanku, namun tersela kedatangan Pak Dayat.
***
“Mau nggak mau. Sebagai manusia, kita pasti akan menikah, Yul.”
Sejak pembicaraan sebelum pelajaran di mulai, Dini terus berceloteh tentang pernikahan. Berusaha merobohkan keyakinanku. Yang sayangnya, usahanya tidak berpengaruh apa pun.
“Aku tahu kamu seperti ini karena ayahmu, tapi nggak semua laki-laki itu kasar, brengsek. Jangan berpikir laki-laki jahat hanya karena ayahmu…”
Dini adalah sahabatku sejak aku duduk di bangku SMP. Entah bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat, apalagi saat tahu kembali bersekolah di SMA yang sama. Tidak ada rahasia yang aku sembunyikan dari Dini, begitu pula sebaliknya.
Aku sungguh tidak tahu bagaimana aku dan Dini bisa bersahabat dengan segala perbedaan yang dimiliki. Seperti Ying dan Yang. Dini adalah warna putih, sedangkan aku hitam. Dini yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, keluarga yang kaya raya dengan orang tua yang begitu harmonis. Aku yang pendiam, tidak sering tersenyum kalau tidak bersama Dini, keluarga yang berantakan dengan ekonomi yang menyekik leher.
Dini adalah sahabatku. Perlu kutegaskan sekali lagi. Oleh karena itu aku hanya diam dan mendengarkan saja apa yang dia ucapkan, walau hatiku sudah meronta dan menepis semua ucapannya. Aku sadar jika dia bersikap seperti ini karena mengkhawatirkanku, karena dia tidak pernah melihat ibunya di siksa di depan matanya sendiri, tidak pernah mendapat berjuta tamparan dan pukulan di sekujur tubuh. Oleh karena itu dia tidak tahu betapa takut dan bencinya aku kepada makhluk berjenis laki-laki.
“Suatu saat, kamu pasti akan menemukan laki-laki yang kamu cintai dan mencintaimu. Saat waktu itu tiba, aku akan jadi orang yang paling bahagia di dunia. Ingat itu.”
Aku hanya terus mengangguk di setiap Dini menyelesaikan kalimatnya. Ia menyeruput es tehnya untuk terakhir kali sebelum melihat jam tangannya dan berdesis heboh, “Jam istirahat mau habis! Aku belum ngerjain matematika!”
Dan drama tarikan tangan dan lari marathon di koridor kembali di mulai.
“Ah, maaf!”
Sekali lagi aku bertabrakan dengan seorang siswa karena tarikan tangan Dini yang membuatku sampai terlepas dari tautannya. Dini, seperti biasa hanya tetap berlari tanpa menoleh untuk melihat kondisiku dan korbannya.
“Oh, lagi?”
Aku menolehkan kepalaku untuk menatap lebih jelas siswa yang baru saja menjadi korban lari. Dia menunjuk wajahku sambil memasang senyuman yang seharusnya tidak ia tunjukkan karena aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba tersenyum seperti itu. Aneh.
“Yang juga menabrakku tadi pagi?”
Keningku mengerut mendengar ucapannya, lalu ingatan kejadian tadi pagi muncul. Aku terdiam. Dan harus melongo karena siswa di depanku saat ini adalah sama dengan siswa yang menjadi korban lari tadi pagi!
“Kamu akhirnya ingat,” ucapnya. Dia tetap tersenyum. Aku menggigit bibir bawah karena malu. Ah, aku tahu kenapa dia tersenyum seperti ini. Pasti dia mengira kejadian ini lucu karena aku dan dia harus kembali bertemu dengan tragedi “korban tabrak lari” Dini.
“Maaf.”
Aku hanya bisa menundukkan kepala, berlalu dengan secepat mungkin dengan wajah memerah. Dini memang selalu menjadi alasan untuk membuatku malu karena sikapnya. Awas saja!
***
Satu hal yang paling aku benci adalah kembali ke rumah sepulang sekolah. Saat membuka pintu, aku pasti akan melihat tubuh laki-laki gembul yang tertidur dengan pulasnya di sofa ruang tamu. Berusaha mengambil langkah sepelan mungkin agar tidak mengusik mimpinya, karena jika sampai hal itu terjadi—
PYAR!
Aku berjengit kaget. Tidak. Bukan aku yang menciptakan suara pecahan itu. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu sambil berjinjit untuk membisukan suara langkah. Tapi matilah aku, mata itu sudah terbuka tepat saat aku di depannya. Tanpa menunggu waktu, tangan kasar itu dengan lihai menarik rambutku.
“Jangan berisik!”
“Bu-bukan aku, Pak.”
Rasanya percuma saja suaraku terdengar memelas dengan memohon seperti ini, toh saat tangannya mulai bertindak, tidak akan ada yang bisa selamat. Kali ini sapu yang menyandar di dinding menjadi barang bukti kekejiannya. Tanpa ampun gagang sapu itu menerjang tubuhku yang sudah terjatuh di lantai. Aku menangis? Tentu saja. Ini sungguh menyakitkan.
“Pak, berhenti! Bukan Yuli yang bikin ribut tadi!” Ibu dari arah dapur berlari sambil memelukku. Aku menangis sesegukan di dekapannya. Pukulan itu berhenti, untuk sesaat.
“Kalian berdua memang sama saja!”
“Ah!”
Kali ini gagang sapu itu mendarat dengan lebih keras di tubuh ibu. Aku yang masih di dekapannya berusaha menampik pukulan-pukulan itu dan melindungi tubuh ibu. Membiarkan memar yang muncul satu per satu di kulit tangan.
“Jangan, Pak!” Aku menjerit. Benar-benar putus asa. Tapi pukulan itu sama sekali tidak berhenti, malah semakin menjadi. Bahkan membuat gagang sapu patah menjadi dua.
Untuk sesaat, aku bisa bernapas lega.
“Sakit, Pak! Bapak kenapa sih jahat? Kenapa selalu mukulin kita?!” Dengan tergugu aku memprotes. Ibu dengan sigap menutup mulutku. Tapi sudah terlambat. Ucapanku sudah cukup untuk menyulut kemarahan bapak ke level tertinggi.
“Dasar anak sialan!”
Aku menutup mata secara spontan saat melihat bapak meraih vas bunga di meja dan mengangkatnya tinggi-tinggi.
Berakhir. Aku akan berakhir.
PYAR!
Suara pecahan vas itu nembuat telingaku bergidik. Aku yang rasanya sudah pasrah dengan rasa sakit yang akan menimpa kepala menjadi ternganga saat membuka mata dan melihat darah yang terciprat di depan wajah. Darah ini bukan milikku, karena aku tidak mengalami rasa sakit sedikit pun. Darah ini milik ibu. Yang kini tengah menyandarkan tubuhnya di dadaku dengan darah yang mengalir di kepalanya.
“Tau rasa kau!” Bapak membentak. Berjalan masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun untuk melihat kondisi perempuan yang selalu berada di sisinya.
“I-ibu…”
Dan aku sendiri masih terlalu tertegun. Mencoba untuk menggoyangkan tangan ibu. Menyuruh ibu bangun, tapi ibu tak kunjung bergerak.
“Ibu…,” suaraku parau. Ketakutan mencekik leher, membuatku sulit bernapas.
“Ibu bangun…”
Ruang tamu dipenuhi dengan isak tangisku. Tak peduli akan laki-laki yang kini mengunci diri di dalam kamar. Yang aku pikirkan hanyalah agar membuat ibuku terbangun! Membuka matanya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja.
“IBU!” Aku berteriak.
Kali ini mencoba membaringkan ibu di lantai dan secepat mungkin berlari ke pekarangan rumah. Meminta pertolongan. Dan ternyata tetangga sebelah rumah telah keluar dengan memasang wajah khawatir, mungkin ia telah mendengar keributan ini sejak awal.
“Tolong...”
Kebahagiaan yang aku dapat detik itu adalah saat melihat anggukannya.
***
Saat kakiku menginjak rumah sakit, hanya satu harapanku: dokter-dokter di sini dapat membantu untuk menyadarkan ibu. Pun ada satu ketakutanku, bisa saja di tempat ini ibu memang tidak akan pernah sadar.
UGD amat penuh siang ini, hampir seluruh ranjang telah terisi. Aku bersyukur ibu masih mendapatkan tempat, tapi kekhawatiran seolah tak pernah berhenti mengetahui belum ada dokter yang kunjung menangani.
“Dok, tolong lihat ibu saya!” Aku berkata dengan buru-buru melihat perempuan berjas ala dokter yang telah menangani seorang balita.
“Di sini harus sabar, Dek. Antri,” jawab sang dokter. Kembali berjalan ke ranjang sebelah pasien. Aku masih mengikuti.
“Kalau harus sabar, ibu saya bisa saja nggak ada, Dok!”
“Sebentar, Dek.”
Mataku memanas mendengar jawaban itu. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan entah mengapa aku malah memberi pandangan benci pada laki-laki yang kini berbaring di ranjang pasien itu. Dengan enak dia telah mendapat perawatan. Lalu bagaimana dengan ibuku?
Aku kembali ke ranjang ibu yang berada di paling ujung. Dua orang perawat di sana. Membersihkan darah, juga mencoba menghentikannya. Air mataku kembali luruh melihat wajah ibu yang begitu damai memejamkan matanya.
Tidak. Aku sungguh tidak ingin mata itu terpejam lebih lama. Aku tidak ingin ibu nyaman dengan tidurnya. Aku ingin ibu bangun. Aku ingin melihat mata itu memandangku. Sungguh. Aku ingin…
“Siapkan ruang operasi.”
Aku tidak sadar sejak kapan ada seorang dokter yang telah berdiri di samping ibuku sambil melihat seberapa dalam luka di kepala ibu. Aku masih berdiri bersama air mataku yang berjatuhan saat orang-orang berseragam putih mendorong ranjang ibu keluar dari UGD. Tante Ira—tetangga sebelah rumah—mengajakku ikut keluar ruangan. Mendudukkanku di bangku tunggu depan ruang operasi.
“Tunggu di sini ya. Tante belikan air minum dulu.”
Aku hanya bisa mengangguk. Pandanganku kosong. Dan aku baru sadar jika kedua telapak tanganku penuh dengan darah. Ini… darah ibu.
“Ibu…”
Drama air mataku pun kembali dipentaskan.
“Ini.”
Aku pikir yang ada di hadapanku adalah botol air minum dari Tante Ira, tapi sebuah tisu basah dari seorang laki-laki yang aku sama sekali tak tahu.
“Bersihkan tanganmu,” katanya.
Aku masih terdiam.
Dia pun diam.
Tanpa aku duga dia berlutut di depanku, meraih kedua tanganku dan dengan pelan menghapus noda darah itu. Tidak lama. Hanya tiga detik—kurang lebih. Setelah kesadaranku kembali dari keheranan, aku segera menarik tangaku kembali sambil memberi tatapan tajam padanya.
“Ah, maaf.”
Dia berdiri, memandangku dengan salah tingkah. Aku memalingkan muka. Apa-apaan. Kenapa ada orang asing yang tiba-tiba datang dan berlaku seperti itu? Tidak sopan.
“Ini.”
Aku kembali memalingkan muka. Bukan karena untuk melihat laki-laki tadi, tapi karena aku tahu itu suara tante Ira.
“Terima kasih, Tan,” ucapku sambil menerima botol air minum dari tante Ira.
“Kapan kamu beli tisu ini?” tanya tante Ira. Aku menoleh pada apa yang ditunjuk perempuan penolongku ini. Benar. Di sana masih ada tisu basah, yang ditinggalkan oleh laki-laki itu.
“Baguslah. Sebaiknya bersihkan tanganmu,” ucap Tante Ira kemudian. Aku mengangguk. Mengambil tisu itu.
***
Aku harus memanjatkan syukur saat tak melihat air muka keruh dari dokter yang menangani ibuku saat keluar ruangan operasi. Di bibir dokter itu tersungging senyum, setidaknya sedikit menenangkan hatiku yang berdentum keras menanti kabar tentang ibu.
“Kondisi ibumu sudah stabil.”
“Hah… syukurlah. Terima kasih, Dok!”
Aku tidak tahan untuk membiarkan air mataku kembali jatuh, tapi ini adalah air mata bahagia. Air mata yang jarang sekali menemuiku.
“Saya bisa menemui ibu saya?”
“Tunggu dulu sampai di pindah ke ruangannya ya.”
“Baik, Dok.”
Dokter itu menepuk bahuku dua kali sebelum pergi bersama senyumannya. Meninggalkanku yang masih berdiri di depan ruang operasi dengan mata yang tak lepas dari punggungnya. Sambil berandai-andai, betapa beruntungnya aku memiliki ayah seperti itu. Yang penuh dengan kelembutan dan senyuman yang menenangkan.
“Yuli, gimana operasinya?” Tante Ira bertanya dengan nada putus-putus. Sepertinya dia habis berlarian dari tempat parkir ke tempat ini.
“Alhamdulillah lancar, Tan,” ucapku. Tante Ira spontan tersenyum lega.
“Ini. Ganti baju dulu. Tadi Tante mampir ke toko sebentar,” Tante Ira berkata sambil menyerahkan sebuah tas padaku. Aku menatap pemberian itu dengan tak enak hati. Betapa tante Ira sangat membantu banyak hari ini.
“Malah melamun. Sana ke kamar mandi. Kamu nggak mau terlihat berantakan saat ibumu sadar, kan?”
Aku mengangguk. Berjalan pelan ke arah kamar mandi dengan hati yang terus merapalkan kalimat janji, “aku harus membayar kebaikan Tante Ira.”
***
Sudah dua hari aku berada di rumah sakit. Kemarin, setelah tiga jam pasca operasi ibu sudah sadarkan diri. Sekuat mungkin aku menyembunyikan air mata di depan ibu. Kembali berubah menjadi gadis yang tegar.
“Kamu belum pulang ke rumah, Yul?” tanya ibu dengan suara lemahnya. Aku menggeleng.
“Kamu tadi nggak sekolah?”
Aku menggeleng lagi.
“Besok sekolah saja, ibu sudah baikan.”
“Aku mau di sini. Jagain Ibu.”
“Terus sekolahmu?”
“Bolos sehari-dua hari nggak apa-apa kok, Bu.”
“Ya sudah terserah kamu.”
Aku tersenyum lebar saat ibu merestui acara bolosku. Lagi pula aku kan tidak bolos karena benar-benar bolos, tapi menjaga ibu. Semisal dipanggil ke ruang konseling, guru-guru mungkin mengerti akan kondisiku.
“Bu, makan ya?” tanyaku sambil meraih nampan yang baru saja datang dari pegawai rumah sakit. Ibu mengangguk.
“Lalu bapakmu gimana, Yul?” tanya ibu sesaat setelah menelan suapan pertama. Senyum yang sejak tadi terbingkai di bibirku menghilang.
“Saat Yuli pulang kemarin, bapak nggak ada di rumah,” jawabku, cuek. Ibu mengangguk-angguk.
“Jangan ngomongin bapak, Yuli nggak suka,” ucapku kemudian. Ibu tersenyum.
“Biar bagaimanapun, dia bapakmu, Yul.”
Aku mendengus. Seperti ini lah ibu, walau sudah dibuat sakit hati dan disiksa sedemikian rupa, masih saja berusaha menciptakan citra baik untuk bapak.
“Kamu sudah makan, Yul?” tanya ibu setelah menghabiskan suapa terakhir.
“Sudah,” jawabku, berbohong.
“Oh ya, biaya rumah sakit ini…” suara ibu menggantung. Aku segera mengangguk sebelum ibu menyelesaikan kalimatnya.
“Sudah lunas kok, Bu.”
“Kok bisa?”
“Pakai uang tabungan Yuli, juga ditambahi sama Tante Ira.”
“Uang hasil kerjamu?”
“Iya.”
Tangan ibu yang yang lemah menggenggam telapak tanganku. Dengan mata yang sendu berkata, “Maaf ya, Nak. Ibu sangat merepotkan.”
Suasana ini membuatku canggung dan aku tidak menyukainya. Aku balik menggenggam tangan ibu. Memberi senyum terbaik yang bisa aku lakukan.
“Ibu bicara apa sih. Sudah jangan berpikir macam-macam. Sebaiknya istirahat lagi, supaya cepat sembuh.”
“Iya.”
Aku duduk termenung di sisi ibu. Mengamati air muka ibu yang sudah payah. Mata senjanya yang kini terpejam dengan tenang. Andai saja setiap hari ibu dapat berisitrahat seperti sekarang, tanpa perlu khawatir mendapatkan cacian dan pukulan dari bapak.
Sejujurnya, permasalahan biaya rumah sakit itu juga kebohongan. Kemarin saat aku ingin membayar, pegawai rumah sakit bilang jika seluruh biaya rumah sakit sudah terlunasi. Sudah tentu pasti tante Ira yang melakukannya. Dan aku semakin merasa tak enak hati dengan tante Ira. Apalagi sejak kemarin sore, tante Ira belum berkunjung ke rumah sakit. Padahal aku sangat ingin mengucapkan terima kasih.
Saat aku masih berpikir tentang bagaimana cara membalas budi kebaikan tante Ira, perutku dengan seenaknya berbunyi nyaring. Berdemo untuk mendapat asupan. Dengan segera aku beranjak dari sisi ibu. Cepat-cepat keluar ruangan. Nanti ibu tahu kalau aku tadi berbohong dan bilang sudah makan.
“Satu bungkus roti cukup, kan?”
Aku mengeluarkan beberapa uang kertas seribuan dari saku celana. Menatap rupiah-rupiah itu dengan menghela napas panjang. Bagaimana bisa kertas lusuh seperti ini menjadi harapan untuk bertahan hidup? Dan orang-orang dengan gila mencarinya? Jika reinkarnasi itu ada, aku mau jadi uang saja.
“Yuli!”
Baru beberapa langkah aku berjalan menjauh dari ruang rawat ibu, tante Ira dari koridor melambaikan tangannya sambil berjalan cepat.
“Tante Ira!” Aku tersenyum, lebar sekali.
“Bagaimana kondisi ibumu?” tanya Tante Ira.
“Alhamdulillah udah baikan. Sekarang Ibu sedang tidur,” jawabku.
Tante Ira mengangguk-angguk, lalu menyerahkan sebuah tas padaku.
“Makanlah. Kamu pasti belum sarapan, kan?”
Aku menatap tas itu dan tante Ira secara bergantian. Rasanya mataku sudah memanas karena rasa haru akan sikap tante Ira. Sungguh baik sekali Tuhan masih memberiku orang seperti tante Ira.
“Terima kasih, Tante.”
“Iya. Sebaiknya kita makan di kantin saja.”
Tante menggandeng tanganku sambil terus berjalan melewati koridor yang penuh dengan aroma khas rumah sakit—obat. Di saat seperti ini, aku merasa berjalan dengan kakak perempuanku. Maklum tante Ira masih tergolong muda, usianya baru 27 tahun. Empat tahun yang lalu pindah ke sebelah rumahku setelah menikah.
“Tante Ira terima kasih banyak.”
“Kamu udah bilang terima kasih tadi, Yul.”
Aku dan tante Ira mengambil duduk di tengah kantin rumah sakit. Suasana pagi ini masih lenggang. Masih beberapa orang yang menikmati sarapannya dengan air muka yang rata-rata sama; sendu dan lelah. Pancaran yang wajar bagi orang yang menjadi penjaga selama semalam suntuk ditambah kesedihan karena orang terkasih tengah berteman dengan obat dan infus.
“Sekarang makan sarapanmu,” ucap tante Ira. Aku mengangguk. Mengangkat sendok ke depan mulut, namun urung. Tante Ira memandangku bingung.
“Saya akan lunasi semua hutan saya, Tan.” Aku menatap tante Ira dengan serius.
“Hutang apa sih? Nggak ada.”
“Untuk membayar biaya rumah sakit ini.”
Dahi tante Ira merengut. “Bukan Tante yang bayar.”
“Bukan?” Dahiku pun ikut merengut, terkejut.
“Bukan.”
Aku terdiam. Jika bukan tante Ira. Lalu siapa?
“Memangnya seluruh biaya rumah sakit ini sudah lunas?”
“Sudah, Tan.”
“Hm, siapa ya? Biar Tante tanyakan pada pihak administrasi.”
Tante Ira beranjak dari kantin. Aku mengekor setelah membereskan makananku yang belum sempat tersentuh.
“Biaya rumah sakit untuk pasian Mulyani, siapa yang melunasi ya, Sus?” Tante Ira bertanya secara to the point kepada pegawai admisintrasirumah sakit.
“Mulyani? Tunggu sebentar ya, Bu.” Perempuan berseragam biru itu mengecek komputer. Menunggu beberapa detik. “Oh, sudah dilunasi oleh Pak Hendri.”
“Pak Hendri?” Tante Yuli mengulang. Menoleh padaku. “Yuli, kamu kenal?”
Aku menggeleng. Pernah mendengar namanya saja tidak.
“Pak Hendri ini salah satu dokter di rumah sakit ini, Bu. Dokter yang juga menangani operasi bu Mulyani.”
“Dokter?!”
Apa yang diucapkan oleh pegawai rumah sakit ini benar-benar membuatku dan tante Ira kompak terkejut. Bagaimana bisa seorang dokter dengan baik hati melunasi biaya rumah sakit yang tidak bisa dibilang murah? Apalagi dokter yang juga menangani operasi ibu.
***
Aku terdiam di depan ruangan Pak Hendri. Ingin mengetuk pintu ruangan orang berhati mulia ini, namun mendengar suara percakapan di dalam ruangan membuatku masih berdiri canggung di tempat ini. Apalagi pintu ruangan Pak Hendri yang tidak tertutup sempurna. Aku baru saja membalikkan badan, berniat untuk datang beberapa saat lagi. Bisa-bisa aku dikira menguping pembicaraan karena terus berdiri di sini, tapi nyatanya aku tetap berdiri saat telingaku benar-benar mendengar pembicaraan di dalam.
“Ternyata meruntuhkan keras kepalamu cukup mudah. Hanya dengan perempuan kamu bisa seperti ini. Pokoknya sesuai janjimu. Kamu harus masuk kedokteran nanti.”
“Iya, Yah.”
“Lagipula siapa dia? Pacarmu? Sampai membuatmu memohon-mohon untuk menyelamatkan ibunya.”
“Bukan.”
“Bukan?”
“Aku hanya… suka.”
“Haha! Dasar remaja! Yang jelas, Ayah sangat berterima kasih dengannya. Sepertinya Ayah harus bersikap baik padanya dan ibunya. Karena dia kamu akhirnya menuruti apa kata Ayah.”
“Apa sih, Yah. Jangan ngomong yang macam-macam pokoknya ke dia.”
“Wah, sekarang kamu takut ya? Biar saja. Biar dia tahu ada laki-laki yang sangat mengagumi dan berkorban untuknya.”
“Ayah!”
“Hahaha!”
“Sudah ah, aku mau berangkat les dulu. Assalamu’alaikum!”
“Wa’alaikumsalam.”
Aku yang terlalu termenung di depan pintu, buru-buru membalikkan badan. Berjalan secepat mungkin menjauhi ruangan Pak Hendri. Berharap laki-laki yang aku rasa anak dari Pak Hendri itu tidak melihatku saat keluar. Laki-laki yang telah membantu ibuku. Laki-laki yang katanya jatuh hati padaku.


 AinunMas
AinunMas








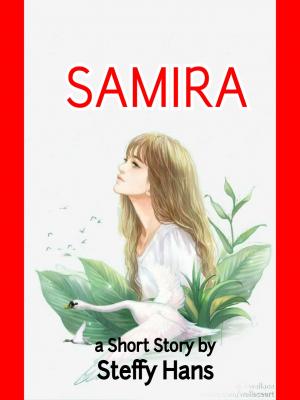



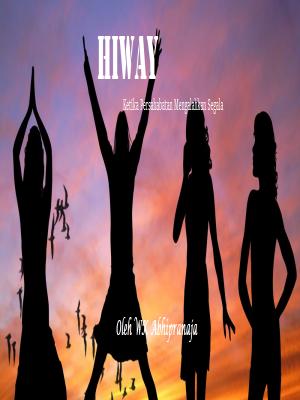

Sedihhh bgt tapi baguss lanjut terus yaa????
Comment on chapter Prolog