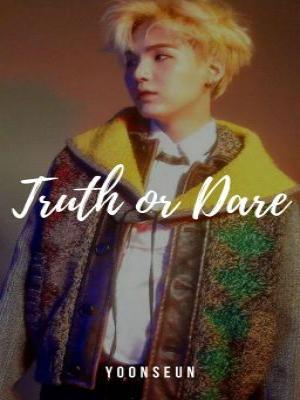Aku berharap dia menyanggah seperti biasanya.
Di saat aku ingin dia membantah apa yang barusan kukatakan, dia justru tidak melakukannya. Sebaliknya di saat aku tidak ingin dia membantah, dia justru melakukannya. Kenapa? Kenapa kali ini dia diam saja? Aku mau dia menertawakan pertanyaanku sampai terbahak-bahak. Aku mau dengan tegas dia mengatakan bahwa pertanyaanku salah. Bahwa situasi dengannya saat ini bukanlah mimpi. Bahwa aku memang berpindah dari ruang kerja ibu ke rumah ini. Bahkan mau dia mengatakan kalau aku gila atau kalau ternyata dia menculikku juga tidak masalah. Asalkan jangan mengiyakan pertanyaanku.
Tanpa sadar mataku sudah mulai berkaca-kaca. Beberapa kali menyembunyikannya dengan berpaling sambil mengerjap-ngerjap. Kalau yang terjadi ini benar mimpi, aku sungguh-sungguh merasakan sakitnya. Kembali terasa seperti saat-saat dimana aku berusaha menahan tangis karena tidak terima kalau ayah benar-benar sudah pergi meninggalkanku dan ibu selamanya.
“Kenapa diam aja? Jadi benar ini cuma mimpi? Jadi artinya dari kemarin aku belum bisa bangun dari mimpiku sendiri?” tanyaku padanya yang masih bungkam. “Bukan. Sebenarnya aku udah bangun kan? Yang kulihat sedang tidur di ruang kerja ibu, itu benar aku. Dan aku harus kembali ke tubuh itu supaya aku benar-benar bisa pulang. Makanya kamu pernah bilang kalau cuma aku sendiri yang tau jalannya.”
Perlahan demi perlahan aku mengerti. Dari awal bagaimana aku tiba-tiba bisa ada di rumah ini hingga akhirnya mencapai detik ini, aku mengerti. Dengan begitu tidak lagi aku kewalahan bertanya-tanya siapa yang membawaku kesini, bagaimana caranya membawaku kesini, dan kemana arah jalan yang bisa menuntunku pulang. Tidak lagi aku repot-repot memikirkan semua itu, karena faktanya jawaban dari semuanya ada pada diriku sendiri. Hanya aku seorang yang tahu.
Kali ini aku memilih untuk menunggunya bicara. Tidak masalah akan diam berapa lama, sebab aku tidak punya sesuatu untuk ditanyakan ataupun dikatakan lagi.
“Hebat. Cepat juga kamu tau.” ujarnya pada akhirnya.
Sekalinya dia bicara, malah makin memperburuk keadaan. Ternyata benar kalau dia sama sekali tidak bermaksud ingin menyanggah. Memberi arti bahwa semua yang kulihat sekarang adalah mimpi, tidak nyata, termasuk dirinya. Tapi bagaimana bisa? Aku masih tidak percaya. Biasanya cerita dalam mimpi tidak pernah jelas. Mimpi juga tidak pernah berlangsung lama. Sulit juga kita akan mendapat mimpi yang sama untuk kedua kalinya. Apalagi situasi dalam mimpi juga tidak pernah konsisten. Bisa tiba-tiba ada di sini, kemudian tiba-tiba ada di sana. Kalaupun ada orang lain yang muncul dalam mimpi, biasanya juga tidak pernah sejelas ini. Sampai saling tatap, saling berbincang, bahkan saling memaki. Makan, minum, kedinginan, kepanasan, kesakitan, seharusnya semua itu tidak terasa. Lantas untuk sekarng, kenapa begini?
Kepalaku berdenyut saking pusingnya mencerna teka-teki yang ada. Entah sejak kapan kedua tanganku sudah memegang kepala. Seolah-olah menyangga agar tidak terjatuh akibat menyimpan beban pikiran yang terlalu berat.
“Maaf. Aku ngga bermaksud mau menyembuyikannya darimu. Aku cuma merasa kalau kamu butuh waktu dan aku memang bukan orang yang tepat untuk bisa menjelaskan. Tapi jangan salah, sambil menunggu orang yang bisa membantumu datang, aku tetap berusaha menuntunmu dan kupikir aku berhasil. Kamu udah lebih dulu tau.”
“Kamu ngga lagi mengerjaiku kan?”
“Ngga.”
Sontak aku berdiri dimana kursi yang sebelumnya kududuki terdorong keras ke belakang. Menimbulkan suara gesekan yang nyaring. Kuabaikan pula lutut sebelah kiriku yang tidak sengaja ikut terbentur kaki meja. Bahkan aku lebih tidak peduli dengan telapak kaki kananku yang baru saja diobati dan diperban.
“Kenapa kamu bilang ngga? Seharusnya kamu bilang iya. Seharusnya kamu bilang, iya aku memang lagi mengerjaimu.” kataku lebih kepada membentak. “Meskipun aku sendiri yang berpikiran begitu, kamu pikir aku percaya? Aku di sini sama kamu udah mau jalan dua hari. Memangnya ada mimpi selama itu? Jadi kalau benar mimpi, terus kamu ini apa? Kamu mencari siapa? Kenapa ceritanya terus berlanjut seolah memang ada kehidupan sendiri di mimpiku ini?”
Pertanyaanku yang terakhir, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertanya itu. Tiba-tiba saja muncul tanpa pernah sekalipun terpikirkan olehku sebelumnya. Sebuah kehidupan sendiri di dalam mimpi. Mungkinkah hal semacam itu ada? Mustahil. Mimpi adalah kehidupan singkat yang dihasilkan dari pikiran seseorang yang sedang tertidur. Tidak mungkin bisa berjalan seperti halnya kehidupan nyata.
Dia menyusulku berdiri. Mengambil dua cangkir yang sudah kosong.
“Semua yang ada di sini adalah hasil dari imajinasimu.”
“Termasuk kamu?” tanyaku dengan suara yang mulai bergetar.
“Semuanya. Sekarang tidur dan pulanglah. Kamu juga udah tau jalan untuk pulang. Ngga ada alasan buat kamu di sini terus.” jelasnya berbalik mengarah pada wastafel.
“Kamu serius ngga lagi mengerjaiku?” tanyaku bermaksud ingin memastikan sekali lagi. Untuk kali ini aku sudah benar-benar menangis.
“Ngga.” jawabnya tanpa sedikitpun menoleh ke arahku. Sibuk dengan wastafel, pancuran air, sabun, dan dua buah cangkir kotor.
Sungguh sulit dipercaya. Aku memang ingin pulang. Pada awalnya aku memang takut berada di sini. Aku juga kesal mendengar ocehannya yang terkadang tidak penting. Namun bukan berarti aku ingin akhir yang seperti ini. Bukan kenyataan bahwa seisi rumah ini, termasuk dirinya, tidaklah nyata. Hanyalah sebuah imajinasiku saja. Jika aku benar sudah pulang dan bangun dari tidur, berarti semua yang kualami ini akan hilang. Aku tidak akan berhadapan dengan orang menyebalkan namun perhatian seperti dirinya lagi. Aneh jika sekarang aku justru merasa sedih.
Aku sudah berbaring di atas kursi kayu panjang di ruang tamu. Tempat dimana pertama kalinya aku membuka mata dan menemukan aku sudah berada di dalam sebuah rumah yang tidak kuketahui. Dalam waktu yang lama, aku terus memandang langit-langit rumah seolah menolak mata untuk terpejam. Walau air mataku sudah tidak lagi mengucur, aku masih merasa sedih. Lelaki imajinasiku ini, entah dia masih berkutat dengan wastafel atau tidak, yang jelas aku sudah tidak melihatnya lagi sejak dia memilih berpisah dengan cara berdiri membelakangiku tanpa mengatakan apapun. Kata ‘berpisah’ mungkin agak berlebihan, mengingat dia bukan siapa-siapa bagiku. Dia hanya sosok yang tidak nyata yang mulai besok tidak akan kutemui lagi.
Baru kali ini aku mendapat mimpi yang terlalu banyak menguras emosi. Baru kali ini aku mendapat mimpi yang terus berjalan layaknya cerita dalam drama. Baru kali ini aku mendapat mimpi bertemu lelaki dengan penggambaran yang nyata, tidak lagi samar-samar dan hilang begitu saja tanpa menyisakan suatu kenangan. Jujur saja alasan yang paling membuatku sedih ketika tahu semua ini hanya mimpi adalah kenyataan bahwa dia tidak nyata.
Dan sepertinya tanpa sadar aku telah membiarkan mataku terpejam. Memberi arti kalau aku sudah siap untuk pulang dan mengakhiri mimpi panjang ini.
Sesuai dengan dugaanku, aku kembali ke situasi yang sama dengan tadi siang. Aku tengah berdiri di lorong rumah sakit yang gelap. Sendirian. Tanpa adanya orang berlalu-lalang seperti keadaan rumah sakit pada umumnya. Perlahan aku melangkah dan kembali menemukan sebuah pintu dengan papan nama yang bertuliskan nama ibu tergantung di sana. Sebelum memutuskan untuk masuk, aku terlebih dulu menarik napas serta menghembuskannya dengan irama pelan selama beberapa kali sampai dirasa cukup untuk membuatku tenang. Barulah tanganku bersiap memegang gagang pintu, membukanya, dan mendorongnya sepelan mungkin. Belum ada setengah terbuka, rasa dingin langsung menyambutku seakan-akan bermaksud ingin mengusirku pergi. Tapi aku mengabaikannya. Aku lanjut melangkah masuk dan tidak lagi terkejut ketika kutemukan tubuhku tengah berbaring di atas sofa.
Aku benar-benar baru sempat mengamati. Keseluruhan yang ada pada tubuhku itu masih sama dengan yang terakhir kali kukenakan. Kemeja panjang biru dengan lengan tergulung, celana jins, kaus kaki bercorak semata kaki,headphone, juga posisi handphone yang kugenggam di atas perut, kemudian sepatu beserta tas yang ada di dekat sofa. Segala sesuatunya masih berada di tempatnya tanpa berpindah satu senti pun. Membuatku bertanya-tanya mengenai suatu hal. Kalau jiwaku, entah bagaimana aku harus menyebut diriku yang tengah berkeliaran ini, pergi seperti sekarang ini, berarti sudah berapa lama aku tidak bangun? Jika hal itu diartikan, artinya sama saja dengan aku hilang. Ibu juga pasti khawatir melihat anaknya tidak sadar selama hampir dua hari. Lantas setelah aku bangun, bagaimana aku harus bersikap?
Jawabannya sama sekali belum terpikirkan olehku. Ada baiknya jika aku pura-pura bingung. Atau mungkin pura-pura sakit kepala. Entahlah. Apapun itu. Pastinya nanti akan ada ide yang tiba-tiba muncul dan bisa saja itu yang justru langsung kulakukan. Yang terpenting sekarang adalah aku harus mendekati tubuhku ini, seperti yang pernah disebutkan oleh lelaki imajinasiku. Mengingat dia sempat bertanya mengenaikenapa tidak didekati saja tubuh itu, membuatku sadar bahwa kelihatannya dia memang sudah berusaha menuntunku. Sengaja menyelipkan kata-kata bantuan di tiap perkataannya agar tidak terlalu kentara. Seharusnya bilang saja dari awal kalau dia bisa dan mau membantuku. Tapi malah bersikap gengsi. Dasar. Sosok dalam mimpi saja bisa semenyebalkan itu.
Tanpa berpikir panjang lagi, dengan berani aku melangkah mendekat. Melihat tubuhku sendiri dalam jarak sedekat ini, membuatku mendadak merinding. Tubuhku begitu kaku bagaikan sudah tidak bernyawa.
Sejujurnya usai mendekat, aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dia tidak memberiku kata kunci lagi. Jadi aku hanya bisa mengandalkan apa yang muncul di kepalaku. Dikarenakan aku ini adalah sebuah jiwa yang tidak sengaja keluar dari tubuh, maka untuk mengembalikannya aku akan kembali masuk ke dalam tubuhku dengan cara ikut tidur bersamanya. Sebisa mungkin aku berbaring sambil mengikuti posisi tubuhku. Kupastikan dari ujung kaki hingga ujung kepala sudah dalam posisi yang sesuai. Setelah itu tanpa kuketahui lagi apa yang harus kulakukan selanjutnya, aku pun langsung memejamkan mata. Dan sekelilingku tampak gelap


 tlotr
tlotr