Pikiran Dika melayang jauh melampaui atap ruang kelasnya. Penjelasan rumus-rumus kimia dan sebutan angka romawi hanya dianggap suara latar yang keluar dari gurunya. Sesekali tangannya menopang kepala, matanya mengawang jauh keluar jendela. Raganya memang di bangku sebelah Daffa, tapi jiwanya entah di mana.
“Ehm ... Dika,” tegur guru Kimianya yang baru menyadari ada anak muridnya yang hanya meninggalkan raga di kelas ini. Buru-buru Daffa menyikut lengan Dika. Nyawa Dika seakan kembali ke tubuhnya, mulai menatap awas ke depan, ke meja guru di mana Bu Evi sudah mengeluarkan aura tegasnya.
“I-iya, Bu,” jawab Dika kikuk.
“Kalau matamu keluar jendela terus, lebih baik kamu cuci muka dulu sana.” Kini hanya suara dari Bu Evi yang mengisi ruang kelas, sebagian anak lainnya melihat Dika dengan tatapan seolah bicara, rasain atau kasian, sebagian lain tak peduli.
“Baik, Bu.” Ia pun keluar kelas dan menuju toilet di lantai bawah. Matahari di tengah hari bersinar terik langsung dirasakan Dika ketika melewati pintu kelas.
Daffa, teman sebangkunya, melirik sekilas kertas yang sesekali dicoret-coret Dika saat terlihat bosan memperhatikan guru di depan kelas.
Handai
Aku ingin bebas
Lepas perlahan selaras
Lunakkan hati keras
Enyah dari yang kebas
Aku ingin bebas
Luruh bagai daun gugur
Lembut angin sentuh nyiur
Atau terbang ke langit luas
Aku ingin bebas
Bukan merasa asing
Bukan masing-masing
Tetapi bersamamu, bebas sampai berbekas.
***
Sejak berjalan menyusuri lorong, cuci muka di toilet, dan kembali ke kelas, Dika seakan banyak memikirkan sesuatu, tubuhnya tidak sesemangat masih jadi anak SMA baru. Kini ia murid kelas 11 semester 2, sudah banyak yang bilang kalau tahun depan ia harus memikirkan matang-matang akan masa depannya. Namun, ia sendiri pun bingung, seakan kehilangan diri sendiri. Itulah yang menyebabkan akhir-akhir ini mulutnya lebih sering merapat dan isi otaknya berisikan benang-benang kusut yang ingin diurainya.
Sebenarnya dirinya siapa, mau apa, dan bagaimana ia akan menjalani kehidupan setelah SMA yang kata orang kebanyakan adalah “kehidupan sesungguhnya”, bukan dianggap anak kecil lagi, harus pula belajar mandiri.
Di antara dua teman dekatnya yang lain, hanya Dika yang masih galau soal pilihan jurusan kuliahnya nanti, tak seperti Daffa yang sudah mantap ingin Arsitektur atau Tama yang ingin jurusan teknik. Sebenarnya ia sudah punya pilihannya, tapi pilihannya itu yang ia pikir akan menimbulkan banyak masalah, terutama izin orang tua.
Dika anak yang biasa-biasa saja, karena itu ia tak tahu berbakat di bidang apa. Makanya sewaktu pemilihan jurusan di awal masuk SMA, ia menurut saja masuk kelas IPA. Daripada masuk kelas IPS yang katanya anak-anaknya banyak yang “terlalu” aktif, pikirannya turut menyetujui. Dika suka teman-teman dari kelas IPA, banyak yang kalem, pikirnya, sesuai dirinya. Apalagi teman-temannya sejak SMP dan awal SMA banyak yang minat ke IPA, ditambah Daffa dan Tama, akhirnya Dika pun jadi anak IPA.
***
“Sekian untuk hari ini, PR-nya jangan lupa dikerjakan yaa, semangat buat ulangan minggu depan, asalamualaikum,” ucap Bu Evi sambil menutup kelas hari ini.
Anak-anak mulai ribut kembali setelah punggung Bu Evi hilang dari balik pintu, beberapa orang mulai mengobrol dengan teman dekatnya, ada juga yang baru beres-beres, ada yang langsung pulang, ada juga seksi kebersihan yang terus mengawasi anak-anak yang piket hari ini.
“Woy! Piket dulu! Itu itu! Masih ada sapu,” teriak Mutia sang seksi kebersihan sambil menunjuk-nunjuk, gelarnya itu didukung rasa awas kalau ada yang kabur piket atau belum bersih, ia menjunjung tinggi slogan “kebersihan sebagian dari iman”.
Tak seperti hari biasanya, kami bertiga lebih banyak diam. Masing-masing dari kami masih punya benang kusut yang belum terurai di kepala, tapi beda jenisnya. Dika masih memikirkan minat bidang kuliahan untuk jalan masa depan, Daffa sepertinya baru berantem sama Aira—teman dekatnya, dan Tama belum pulang ke rumahnya juga sejak minggu lalu. Kebanyakan orang melihat kami biasa-biasa saja, tenang, dan kalem. Sesungguhnya ada gemuruh yang diredam dalam dada kami.
“Daf, Tam, balik duluan ya,” pamit Dika sambil membawa ransel dengan sebelah bahu dan menepuk bahu mereka.
Saat di pintu, ia menoleh sebentar ke arah lapangan, sudah banyak siswa yang bermain bola, di tangga sebelah lapangan pun sudah banyak siswa yang lalu-lalang karena kelas baru dibubarkan. Langit-langit yang tadi hanya berisikan suara guru kami, kini berubah 180 derajat, entah apa yang kebanyakan orang omongkan tapi semuanya berbaur. Bukan kali pertama ia merasakan kesepian di antara keramaian.
***
Dika segera menuju parkiran, mengendarai motor, dan langsung pulang. Kali ini ia melambatkan laju motornya, menikmati embusan angin yang menerpa kulit dan seragam putih abunya, serta gemuruh suara kendaraan yang membungkus jalanan. Matanya tetap awas, tapi ada kelelahan di sana, entah lelah karena apa, akhir-akhir ini ia merasa tak berdaya. Padahal tubuhnya baik-baik saja.
***
Akhirnya ia sampai di rumah sederhana yang ia tinggali bersama kedua orang tua, Dika cuman punya satu kakak perempuan yang usianya agak jauhan. Dika punya keluarga yang baik, teman-teman yang menyenangkan, tapi rasanya ada yang kurang.
Suatu malam saat tengah mengerjakan PR-nya, ia mengambil secarik kertas lalu menulis di sana.
Jenuh, Jatuh
Suatu hari, di awal tahun.
Pernah gak sih ngerasa kita gak bisa ngelakuin apa-apa?
Gak punya bakat apa-apa?
Pernah gak sih ngerasa kita gak seru dijadiin seorang teman?
Nyebelin atau gak asik?
Pernah gak sih ngerasa kita gak tau mau dan harus ngapain lagi.


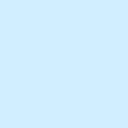 cantikahanah
cantikahanah








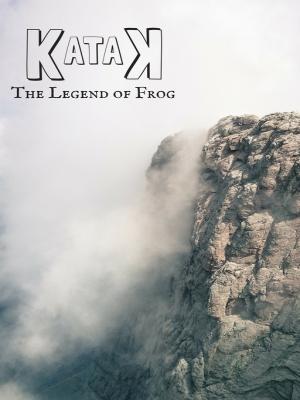


Mantap cantikaaa, teruskan ya semoga jalan menjadi penulis lancar sukses dan dapat memberikan inspirasi lewat tulisanmu seperti yang udah kamu lakukan padaku.
Comment on chapter 1. Gerbang Masa Lalu