Satu siang pada hari-hari santai mereka. Hari setelah badai ujian itu reda. Berbagai ujian dan anak-anaknya sudah habis mereka jalani. Pengumuman kelulusan perguruan tinggi pun lancar tiada hambatan. Dika, Daffa, dan Tama bisa bernapas lega. Berkali-kali mengucapkan syukur. Memang benar, setiap kesulitan ada bersama kemudahan.
Satu siang itu, Dika berinisiatif mentraktir mereka es krim di kafe langganan mereka. Dalam rangka banyak hal yang mereka syukuri kehadirannya. Dalam rangka juga dia yang paling tua di antara mereka bertiga dan paling pertama dapat pengumuman kelulusan di perguruan tinggi.
Daffa yang paling menunjukkan ekspresi senangnya waktu Dika mengajak mereka ke kafe dan dia yang berniat membayarnya.
“Bener deh, ini es krim terenak, merek-merek terkenal aja lewaaaaat,” celetuknya setelah mencicip satu kali es krim cokelat berbalut waffer. Embun es yang sedikit mengganggu kacamatanya pun tak dihiraukannya, Daffa keasyikan menikmati es krim gratisannya.
“Lebay ah,” balas Tama tak kalah dingin seperti es krim vanilla bertabur kacang.
“Nggak tau terima kasih dasar tu anak,” balas Daffa lagi bercanda sambil menunjuk Tama dengan ekor matanya.
Yang dilihat cuman menatap balik dengan hening sekejap lalu berkata, “Thanks, Dik. Semoga rezekinya lancar terus ya, semoga ke depannya bukan es krim aja, tapi—”
“Bener-bener nggak tahu diri,” ejek Daffa, lalu mereka bertiga tertawa.
“Hahaha santai. Siaplah. Harusnya yang lagi berbunga-bunga tuh yang traktir,” kata Dika sambil melirik Daffa yang baru selesai menghabiskan es krim terenak menurutnya.
“Siapa? Aku?” Yang ditunjuk peka. “Nggak tuh.” Yang tadinya bercahaya jadi agak meredup.
“Loh? Bukannya kemarin hunting foto ke daerah yayasan tempat tinggal Aira? Terus keliatan seneng lagi,” kata Dika.
Daffa tertawa kecil sendirian, agak hambar. “Nggak semua yang tertawa bebas duka, cuman yang berduka juga selalu ada alasan untuk bisa tertawa. Tinggal pilih kan? Mau senang atau sedih, kita yang milih. Lagian sekarang udah biasa ajalah, udah bakal lupain Aira kok, santai ajaaa.”
“Kalau mau lupa malah semakin ingat, Daf. Terima aja. Cerita gih,” kata Tama.
“Besok deh, aku ajak kalian ke sana. Biar nggak usah ungkit dia lagi. Ehm ... lebih tepatnya minta bantuan sih, karena orang di yayasan nyuruh aku ke suatu tempat tapi belum tau arah ke sananya.”
“Siap, besok aku aja yang bawa mobil,” kata Tama mantap.
***
Besoknya, mereka bertiga dengan kaus putih dan kemeja motif kotak-kotak mengunjungi yayasan tempat Aira tinggal.
“Kok kita bertiga bisa samaan gini nih?” tanya Daffa heran, nggak biasanya mereka sehati itu.
Dika dan Tama malas menjawab pertanyaan basa-basi busuk ala Daffa itu. Pasalnya ruangan asing yang mereka tempati tidak cocok untuk saling bercanda. Ruang tunggu di yayasan itu bertembok putih, bernuansa klasik, banyak barang kuno yang disimpan apik untuk mendekor ruangan persegi yang muat sekitar 10 orang itu. Tak lama, penjaga yayasan menghampiri mereka. Seorang Papa-Papa, nggak terlalu muda atau tua, pembawaannya tenang, langsung tersenyum dan duduk di hadapan mereka.
“Mau cari Aira, ya?” tembaknya langsung.
“Maaf, Pak. Saya balik lagi nih hehe,” kata Daffa.
“Iya, maaf mengganggu, Pak. Kami juga teman-teman dekatnya Aira. Cuman ingin tau aja gimana kabarnya dia sekarang,” tambah Tama.
“Kemarin-kemarin saya udah cerita dikit sih sama Daffa, ya. Cuman keburu ada tamu jadi nggak bisa cerita agak panjang. Aira udah pindah keluar kota sama ayahnya. Kami sarankan ia menlanjutkan kuliah di luar sambil tetap menemanti ayahnya berobat di salah satu rumah sakit milik kolega kami, di sana lebih baik fasilitasnya. Memangnya dia nggak cerita sama kalian?”
“Nggak, Pak. Aira juga nggak pamitan, kami takut ada salah sama dia.” Dika akhirnya berbicara.
Papa itu tertawa kecil. “Nggak usah khawatir sama itu. Aira anaknya baik. Pasti kalian sudah dimaafkan kalau ada sesuatu yang salah pun. Mungkin dia punya alasan kenapa nggak mau cerita banyak sama kalian.”
“Padahal dulu dia terbuka banget sama kami, Pak. Jadi merasa kehilangan seorang teman aja,” kata Daffa. “Oh, iya ... kemarin-kemarin Papa baru bilang Aira pindah aja dan kasih tau tempat yang biasa didatangi Aira, tapi saya kurang tau daerah kaki gunung. Kami boleh minta alamat lengkapnya?” tambahnya.
“Oh iya, sebentar ....” Punggung Papa itu menghilang sejenak dari balik pintu lalu kembali lagi dengan secarik kertas.
“Ini. Semoga tempatnya ketemu ya, nggak susah kok. Cuman beberapa rumah di sana. Ini villa salah satu kontributor yayasan. Kalau pemiliknya lagi di sana, Aira suka diajak ngadem di sana.”
“Wah, iya ... makasih banyak, Pak.”
“Ngomong-ngomong, Daffa ini keliatan yang paling semangat cari dia, emangnya ada apa, ya?” tanya Papa itu usil sambil tersenyum.
“Hahaha, saya cuman merasa dia orangnya.”
***
Tak banyak pikir lagi, mereka bertiga langsung melesat ke alamat yang dituju. Daerah kaki gunung. Nggak begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Semakin lama perjalanan, hawanya semakin sejuk, pemandangan yang mereka lihat pun semakin hijau. Entah apa tujuan mereka nanti, seenggaknya mereka berhasil melepaskan penat dan liburan sekejap karena perjalanan ini.
Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di sebuah villa yang berada di antara hutan-hutan kecil, lahan rumput yang terbentang di mana-mana termasuk ilalangnya, juga deretan villa-villa lain yang berjarak agak berjauhan, cuman ada sekitar 5 villa di kompleks ini. Cuitan serangga alam yang memenuhi langit, suasanya begitu sejuk dan damai. Mereka baru bertemu satu-dua orang selama perjalanan. Itu pun yang mengangkut beberapa bahan makanan mentah yang baru diambil dari kebun.
“Yakin yang ini?” kata Dika yang pertama kali melontarkan kata-kata setelah mereka keluar dari mobil.
“Alamatnya sih gitu,” balas Tama sambil melihat secarik kertas yang tadi diberikan Papa di yayasan.
Seketika ada seorang ibu-ibu seperti penjaga villa atau yang mengurus di sana.
“Ada apa ya, Den?”
“Eh, permisi Bu, saya mau tanya ini betul rumahnya Pak Subianto?” ujar Daffa sopan.
“Iya, betul. Tapi ini cuman rumah yang ditempati sesekali kalau keluarga Papa ke kota ini. Pak Subianto tinggal di luar kota.”
“Oh gitu ... maaf, ini dengan ibu siapa, ya?” tanyanya lagi.
“Oh iya ... saya Bu Marni, dibolehin Papa tinggal di sini sambil bantu-bantu. Anak saya yang perempuan juga jadi tinggal di sini.”
“Kalau Ibu kenal sama perempuan yang namanya Aira?”
“Neng Aira? Apal pisan atuh eta mah. Iya kenal. Dia yang kadang-kadang suka main ke sini sama anak saya. Sama-sama yang dibantu keluarga Pak Subianto. Sekarang mereka jadi bareng-bareng lagi kuliah di luar kota.”
“Aira beneran pindah, Bu? Nggak ada kabar lagi?”
“Iya, Den. Ya gitu aja. Jadi lebih tertutup. Katanya sih jadi lebih sibuk, cuman dia bilang nggak usah khawatir, Aira baik-baik aja. Oh iya ... ini teh temennya Aira?”
“Iya, Bu. Perkenalkan saya Tama, ini Dika, dan Daffa.”
“Daffa?”
Ketiganya langsung saling pandang.
“Sebentar ...,” sahut ibu itu hendak meninggalkan mereka di luar pagar. “Eh ... sekalian masuk aja atuh yuk!” ajaknya kemudian.
***
Lantai berlapis kayu mengkilat, cat putih, perabotan yang didominasi kayu, jendela yang besar-besar, dan sofa empuk yang mereka duduki membuat betah. Terasa menyatu dengan alam, nggak musuh-musuhan.
Tidak ada yang banyak bicara, entah bingung, menikmati suasana yang sejuk, atau fokus menyesap teh manis hangat yang disajikan Bu Marni. Sementara pembuat tehnya kembali lagi ke belakang, punggungnya hilang di balik salah satu ruangan yang diduga salah satu kamar di villa itu.
“Nah ini ...,” kata-kata yang pertama keluar dari Bu Marni saat menemui mereka lagi di ruang tengah sambil menaruh satu lembar foto di atas meja. Foto yang dicetak dengan kertas foto mengkilap dan ada tulisan di belakangnya ketika Bu Marni melihat lagi untuk memastikan benar foto itu yang sejak tadi dia cari.
“Foto ini Ibu temukan waktu beresin kamarnya Neng Aira kalau nginep di sini, sebenernya kamar anak Ibu cuman mereka suka berbagi. Neng Aira kalau ke sini paling-paling juga ngadem, obat suntuk katanya. Paling juga cuman duduk-duduk di teras depan sambil liat pemandangan di bawah atau foto-foto di bukit yang ada ilalangnya,” ceritanya lengkap.
“Aira juga suka foto-foto, Bu?” tanya Daffa antusias.
“Iya, sering dipinjemin sama Pak Subi. Neng Aira sama anak ibu mah udah dianggap keluarga sendiri sama beliau, karena anaknya sendiri nggak tau pada di mana ... ya urusan pribadi keluarga.”.
***
Setelah mengobrol ringan beberapa lama, mereka pamit.
Saat mobil Tama mulai menuruni bukit, di kaca jendela sebelah kiri, Daffa bisa melihat kumpulan ilalang itu. Tanpa ragu, ia meminta berhenti sejenak dan menikmati alam sekali lagi.
Dika dan Tama langsung duduk di atas rumput, melihat hamparan pemandangan di bawah sambil berbincang-bincang. Dika jadi punya inspirasi lagi untuk menulis. Semesta mengiriminya inspirasi lagi. Pemandangan menakjubkan ini menjadi tintanya lagi.
Kesadaran Satu Rasa dalam Semesta
Semesta berisikan langit dan bumi. Kehadiran manusia berada bersama alam raya. Angkasa dan tanah membantu manusia melangsungkan hidupnya. Hujan yang turun menumbuhkan biji-bijian dan angin mengantarkan benang sari ke putik agar menghasilkan buah untuk manusia makan. Tanah menjadi landasan manusia untuk bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari ke mana saja.
Terkadang manusia lupa kehadiran alam yang sangat berarti. Alam seakan sudah menyatu dalam kehidupan sehingga keberadaannya dilupakan. Kehadiran alam yang seimbang baru dirasa ketika bencana-bencana mulai berdatangan. Tidak sedikit yang disebabkan manusia. Beberapa orang masih berpikir buang sampah sembarangan adalah hal biasa, karena cuman sampah kecil atau sedikit. Padahal sedikit-sedikit bisa menjadi bukit. Ketika ada hujan besar lalu banjir, manusia saling menyalahkan, tetapi tidak melihat perbuatan dirinya sendiri terlebih dahulu.
Aktivitas-aktivitas buruk yang terlihat sepele bisa berpengaruh besar terhadap alam. Contohnya saja lupa mematikan lampu saat siang, lupa mencabut pengisi daya ponsel padahal tidak terpakai, atau lebih memilih memiliki AC daripada jendela besar. Terkadang teknologi membuat manusia lupa. Kebiasaan terkadang itu lama-lama menjadi sering. Baru tersadar ketika lapisan ozon menipis dan udara semakin panas karena bumi kehilangan pelindungnya secara perlahan.
Manusia perlu mengingatkan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Alam adalah sahabat manusia. Alam adalah tempat tinggal manusia yang diberikan Tuhan untuk dijaga. Lebih baik saling mengingatkan untuk mencegah daripada baru tersadar saat alam sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia
***
Mereka masih di sana, Dika mulai berhenti mencoret-coret buku catatannya, Tama mulai nyaman menikmati langit sambil beralaskan rumput, sedangkan Daffa lebih banyak diam dan sendiri. Menyusuri sela-sela ilalang, menjejak tanah-tanah, merasa-rasa apa yang kira-kira yang biasanya Aira rasakan. Ia baru mengaku, ia merindukan sosok itu.
Akhirnya Daffa bergabung bersama dua karibnya. Duduk di paling ujung sambil menggenggam foto yang diambil Aira, foto yang diberikan Bu Marni.
Daffa melihat foto itu sekali lagi, membaca tulisan di belakang foto itu lagi.
Biarkan aku dan kamu menjadi diri sendiri di kerasnya arus kehidupan.
Sebuah rasa yang sama belum berarti satu tujuan.
Apalagi ditakdirkan.
Daffa masih bingung maksud tulisan itu.
Namun, hatinya merasa sudah lega, pertanyaannya selama ini seolah terjawab semua. Ia harus mengikhlaskan.


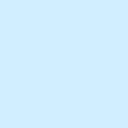 cantikahanah
cantikahanah



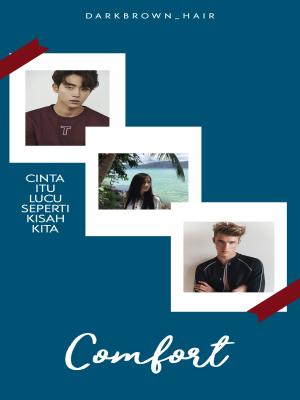







Mantap cantikaaa, teruskan ya semoga jalan menjadi penulis lancar sukses dan dapat memberikan inspirasi lewat tulisanmu seperti yang udah kamu lakukan padaku.
Comment on chapter 1. Gerbang Masa Lalu