Kenangan beberapa tahun lalu terhisap lagi di ruangan kafe itu. Dika tersenyum mengenang segala perjuangannya. Semesta tak hentinya mempersiapkan yang terbaik untuk hasil keringat yang jatuh karena karsa asa. Setelah kuliah pun, nggak lama ia dapat kerja di penerbitan milik om-nya Tama, ternyata Pak Bowo yang pernah memarahinya menjadi mitra penerbitan tersebut, ia jadi lebih mendukung kerja keras Dika sehingga kariernya berjalan lancar. Setelah bermaafan pun mereka menjadi mitra kerja yang seperti keluarga sendiri. Dika menikmati dan bersyukur akan kehidupannya, meski nggak selalu mulus dan berhenti sejenak, ia tetap berjalan dan berlari untuk terus bermanfaat sampai roda kehidupannya mencapai batas akhir hayat.
***
Kini giliran Daffa yang terhisap ke masa-masa manisnya remaja. Sebelum masuk SMA, Daffa udah sering dengar atau baca dari orang-orang kalau masa SMA itu masa yang paling indah. Saking klisenya, mungkin tulisan itu sudah menempel di mana-mana, di buku-buku, film, selebaran di jalanan, tiang listrik, bahkan jidat Dika yang agak lebar itu. Namun, Daffa masih percaya nggak percaya, sebelum ketemu Aira ....
Waktu itu kelas sudah hampir kosong, yang tersisa tinggal mereka bertiga. Oh iya, ditambah sang KM. Lagi asyik-asyiknya ngobrol nggak jelas. Tiba-tiba sang KM bersuara setelah melihat ponselnya.
“Daf, bisa nggak tolong fotokopiin materi Biologi? Pak Gus baru ngirimin nih. Aku harus cepet ke rumah sakit jenguk mama.”
“Kenapa nggak nyuruh Dika atau Tama?”
“Yaelah, kamu yang ada di hadapan.”
“Hmm, iya deh.”
“Udah dikirimin lewat LINE, ya. Fotokopi sebanyak jumlah anak kelas,” perintah sang KM.
“Anak kelas ada berapa sih?” tanya Daffa sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam tas.
“Tiga puluh dua,” sahut Tama.
“Jangan lupa lho. Udah ya duluan, keburu hujan.” Kalimat terakhir sang KM sebelum keluar kelas, tas gendongnya sudah tersampir di sebelah bahunya.
“Yo, hati-hati, Di. Salam buat mamamu, semoga cepet sembuh,” kata Dika.
“Makasih, ya!” balas Andi sambil melambaikan satu tangannya sebelum menghilang dari balik pintu.
“Kalian pulang duluan aja deh, aku mau fotokopi deket sekolah aja.”
***
Titik-titir air yang mulanya turun satu-satu, kini bergerombol. Mereka yang asalnya sendiri-sendiri, sekarang jadi terlihat satu kelompok yang kompak membasahi bumi. Jalanan yang asalnya berpolusi, jadi diredam oleh air yang sejuk. Motor-motor mulai menepi mencari tempat berteduh. Langit mulai berlukiskan cat kelabu. Angin mengembus, melewati kisi kacamata baru Daffa yang kini jadi berembun. Sekejap saja, kumpulan air itu seperti mau unjuk rasa, turun cepat membentuk hujan yang akan lebat. Kaki-kaki Daffa mulai mempercepat langkah, tas gendongnya mulai dijadikan payung darurat. Genangan air yang baru terbentuk dihindarinya secara hati-hati. Kecepatan kakinya jadi makin bertambah seiring kecepatan air itu turun ke bumi. Kakinya bukan menuju tempat fotokopian lagi, melainkan halte terdekat yang bisa dijamahnya untuk tempat berteduh.
Lega. Tubuhnya sekarang punya tempat berlindung. Atap halte berbahan seng tebal menjadi tamengnya. Rintik air beraturan membentur atap itu, tercipta irama yang khas dari kehadiran hujan sore itu. Bangku panjang yang menyatu dengan pondasi halte basah, jadi ia cuman bisa berdiri melihat pemandangan syahdu dari kumpulan air yang seperti menyisir langit dan bumi.
Beberapa detik menatap jalanan, ia baru menyadari ada tangan seseorang yang menjulur ke luar halte, bermaksud ingin disentuh titik-titik air seperti atap halte.
“Kamu harus kehujanan kalau mau kena air hujan,” kata Daffa SKSD.
“Aku suka hujan tapi nggak suka kehujanan. Lagian hujannya lagi besar.” Orang itu merespons celetukan Daffa, ternyata seorang gadis seusianya.
“Hmm, banyak orang yang udah bilang gitu.”
“Sama banyaknya kayak orang-orang penikmat hujan dan senja juga?” balas gadis itu sambil sedikit tertawa. Daffa jadi ikut tersenyum.
“Mungkin,” balasnya lagi. “tapi aku lebih suka langit, bangunan-bangunan, dan dedaunan hijau.”
Mungkin kalau Dika atau Tama yang diajak ngobrol bakal balas, “Sori ye, Daf. Nggak nanya.”
Tapi gadis itu berkata, “Kamu suka cokelat panas juga nggak?”
“Suka,” jawab Daffa meski sedikit bingung kenapa tiba-tiba obrolan ini jadi ke arah menu minuman.
“Kalau fotografi?”
“Suka juga.”
“Hmm.”
“Kenapa?”
“Nggak apa-apa.”
Daffa akhirnya menatap gadis itu dengan pandangan curiga, pasti ada apa-apa.
“Nggak usah lihatin sampai segitunya. Kamu cuman mirip seseorang,” kata gadis itu tak acuh.
“Siapa?” tanyanya kepo.
“Rahasia.”
“Ohh oke oke, maaf udah berlagak kepo sama orang yang baru kenal.”
“Emang kita kenal?”
“Oh, kamu mau kenalan?”
Gadis itu jadi memalingkan pandangan, kembali kepada jalanan yang basah sehabis diguyur hujan, kini rintik-rintik itu tak sebanyak tadi. Gerimis kecil yang kini mengambil peran membungkus kota, motor-motor yang berteduh kembali keluar dari sarangnya.
“Sori sori kalau ganggu. Namaku Daffa. Anak SMA Arjuna Bangsa.”
“Arjuna Bangsa? Aku juga,” katanya kembali melihat Daffa, kini lebih memperhatikan lengan atas seragam sekolahnya, tapi tak terlihat bet sekolah di sana karena tertutup jaket jeans, sama seperti miliknya.
“Oh, ya? Kelas berapa? Kok kayak nggak pernah lihat.”
“Kelas 12 IPS 2. Emang nggak aktif di sekolah sih, tiap bel juga langsung pulang.”
Daffa cuman berlagak “ohh” sambil jaga jarak aman.
“Kalau kamu?” tanya gadis itu.
“Kelas 12 IPA 1. Pantes ya kayak bumi sama langit, padahal satu atap.”
Ada tawa kecil sesaat lalu senyap.
“Aku duluan, ya? Senjanya udah hampir habis, mau fotokopi berkas kelas dulu juga,” kata Daffa hendak pamit.
“Oh, iya ....”
Baru saja Daffa hendak melangkah, gadis itu berbicara lagi.
“Eh, setahuku fotokopi di Pak Makmur lagi nggak bisa sih, kalau kamu mau, aku bisa bantu fotokopi di rumah, udah ada printer yang bisa fotokopi juga.”
Daffa agak terkejut tapi berusaha jadi anak cool, padahal biasanya dia cengengesan.
“Oh, ya? Boleh tuh, beneran nggak apa-apa?” Padahal bisa saja dia fotokopi di tempat lain, tapi entah kenapa ada perasaan hatinya yang ingin berteman dengannya.
“Gak apa-apa kok, lagian tintanya suka kering kalau nggak dipake.”
“Wah, makasih banget loh. Bayarannya aku traktir cokelat panas di kafe seberang, ya?”
Kalau ada Dika dan Tama, pasti mereka sudah nyorakkin, “Modus, modus, modus!”
“Nggak usah kok, nggak apa-apa,” tolaknya sambil tertawa sungkan.
“Kamu suka cokelat panas juga, kan?”
“Iya sih ... tapi—”
“Sekali aja deh buat gantiin fotokopi. Yok!”
***
Sebenarnya gadis itu belum mengiyakan, tetapi Daffa lebih dulu beranjak menuju kafe di seberang jalan untuk membelikannya cokelat panas. Gadis itu jadi mengikutinya di belakang, masih sungkan untuk berjalan berdampingan.
Akhirnya mereka membeli cokelat panas di kafe itu. Namun, ketika hendak pulang, hujan kembali mengguyur deras. Mereka jadi duduk dulu di kafe itu sambil menunggu hujan agak reda, sambil menikmati cokelat panas kesukaan mereka tentunya, sambil mengobrol sebentar.
“... ayahku seorang disabilitas, ia kesulitan bicara. Ibu sudah meninggal. Jadi aku yang sering mengurusnya. Sehabis pulang sekolah, aku langsung ke yayasan, kami diperbolehkan tinggal di sana. Rumah kami sebelumnya yang ditempati bersama ibu, kami jual untuk pengobatan ayah,” cerita gadis itu.
“Oh begitu ...,” balas Daffa turut prihatin. “tapi tadi bukannya kamu bilang di ‘rumah’ ada printer yang bisa fotokopi?”
“Iya, rumah yang kumaksudkan itu yayasan. Rumah baruku. Pemiliknya sangat peduli sama orang-orang dan keluarga disabilitas, kami di sana jadi punya keluarga baru. Banyak hal yang kupelajari di sana, terlebih dari orang-orang yang mengajarkan arti hidup. Awalnya aku sedih banget, dulu sering diejek sama teman-teman sekolah karena punya ayah disabilitas, lalu ibuku meninggal. Tapi, Tuhan memberikan kesulitan bersama kemudahan. Datangnya nggak bergantian, datangnya bersamaan. Aku tetap diberi kehidupan dari orang lain, juga menjalani dengan syukur kehidupanku sekarang. Aku masih punya ayah, masih punya orang-orang yang mau membantu, mau bersamaku nggak cuman di saat terik, tapi tetap memberikan payung saat hujan.”
Daffa terkagum mendengar ceritanya. Seorang gadis yang ditemuinya membuatnya merasa dirinya juga beruntung dan bersyukur.
“Teman-teman kamu gimana?”
“Aku cuman punya sedikit teman. Kebanyakan orang nggak mau mendengarkan dulu, mereka cuman lihat sisi permukaan tanpa tahu dasarnya. Aku cenderung pendiam sih, karena meski aku menjelaskan juga mereka nggak memahami, mereka cuman mau menjawab.”
“Kenapa kamu percaya menceritakan semua itu sama aku?”
Gadis itu agak terkejut dan tersadar, tetapi pancaran mata Daffa kembali menghangat.
“Ehm ... nggak tahu, rasanya kamu memancarkan aura pertemanan yang baik,” jawab gadis itu polos. Daffa hampir tersedak karena ia mendengarkan sambil menyesap cokelat panasnya yang takut keburu dingin. “Aura yang sama kayak teman-teman baikku, kayak paman dan bibi di yayasan, kayak ayahku.” Mata Daffa kembali berbinar.
“Serius?”
Gadis itu tersenyum. “Hal-hal yang kamu suka tadi, sama kayak ayahku.”
“Oh, ya?” katanya sedikit terkejut. Kalau Daffa sadar, hari ini dia jadi sering melontarkan kata itu.
Gadis itu mengangguk lalu menyesap kembali cokelat panasnya.
“Kapan-kapan aku mau bertemu ayahmu.”
“Boleh.”
Setelah itu mereka mengobrol topik lain, cuman sebentar, karena hujan sudah reda dan langit semakin gelap, kali ini bukan karena hujan, tetapi waktu malam yang akan mengambil peran.
“Senang berteman denganmu, sampai jumpa lagi ....” Kalimat Daffa terpotong karena ia sadar belum tahu nama gadis di depannya ini yang sudah menceritakan sebagian kisah hidupnya.
“Aira.” Gadis itu membantu melengkapi kalimatnya. “Senang juga berteman denganmu, Daffa.”


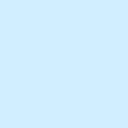 cantikahanah
cantikahanah











Mantap cantikaaa, teruskan ya semoga jalan menjadi penulis lancar sukses dan dapat memberikan inspirasi lewat tulisanmu seperti yang udah kamu lakukan padaku.
Comment on chapter 1. Gerbang Masa Lalu