Besok paginya sama seperti pagi-pagi biasanya, rutinitas yang sama. Bangun, ibadah, olahraga, makan, mandi, sekolah, belajar, ngerjain tugas, tidur, bangun lagi. Semuanya baik-baik aja tapi kenapa merasa ada yang kurang, ya?
Lamunan Dika tersadar oleh teguran mamanya.
“Baru tau mama kalau anak zaman sekarang ke sekolah pake kaus kaki cuman sebelah,” ledek mamanya yang sebentar mengalihkan pandangan dari koran paginya.
Dika cuman nyengir lalu balik lagi ke kamarnya.
“Hari ini kaus kaki, kemarin jam tangan, besok apa lagi ya ....” Mamanya terus saja menggoda Dika yang akhir-akhir ini selalu kelihatan nggak fokus. “Bukannya mama nggak percaya sama kamu, cuman kalau ntar masuk bisnis atau teknik pasti masa depannya aman lho, Dik,” tambah mamanya lagi.
“Hari ini nyaranin bisnis atau teknik, kemarin kedokteran, besok apa lagi ya ....” Dika nggak mau kalah.
“Eh tapi bener lho, Dik. Kemarin anaknya Bu Asti yang dokter itu, udahlah mantap gajinya. Keluarganya pasti hidup sejahtera, bahagia—”
“—damai sentausa.”
“Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Bukannya mama khawatir, mama cuma sayang sama kamu, Dik.”
Wajar aja kalau mamanya sedikit khawatir sama anak bungsunya. Dika harapan terakhir orang tuanya untuk diberikan yang terbaik. Kakak perempuannya sudah berhasil menjadi sarjana dan tak lama setelah bekerja langsung menikah. Kak Dita sudah bukan tanggung jawab penuh orang tuanya lagi, sudah hidup bersama suaminya di luar kota. Jadi, mamanya sekarang seakan menganggap Dika sebagai anak tunggal.
“Makasih ya, Ma. Siapa juga yang nggak mau hidup serba cukup lahir batin. Insyaallah Dika bisa tanggung jawab sama pilihan sendiri, Ma. Aku ingin menjalaninya karena suka. Rezeki nggak akan ke mana, bakal ngikutin, lagian udah dijamin juga, kan? Dika minta doanya aja biar dikasih yang terbaik,” pungkas Dika sebelum pamitan.
“Iya deh, belajar yang bener ya,” ucap mamanya ketika disalami.
***
Baru beberapa meter keluar dari perumahan rumahnya, kemacetan pagi segera menyambutnya. Jam-jamnya pergi ke kantor, berangkat sekolah, dan aktivitas pagi lainnya membuat sesak jalanan. Berbagai macam kendaraan hambur berbaur. Ada sopir angkot yang nggak sabar antre, pengendara motor yang membuat kendaraannya lincah menyalip setiap ada celah kosong, dan petugas polisi yang sudah bingung bagaimana mengatur orang-orang panik terlambat masuk. Bahkan udara pagi yang diharapkannya memanjakan hidung, malah polusi asap yang jadi asupannya.
Untung sih Papa polisi itu bisa melakukan pekerjaannya, kalau aku bakal telat nggak, ya? Duh, apa gara-gara tadi debat dulu sama mama jadi keburu kena macet, rutuknya dalam hati sambil melihat jam tangan yang melingkar di lengan kiri. Lima menit lagi bel masuk! Kalau bukan karena begadang ngerjain tugas, kesiangan, lupa pakai kaus kaki, ngobrol sama mama, mungkin pagi ini berjalan sempurna, pikirnya lagi.
Ya ... mau gimana lagi. Akhirnya ia terus-terusan merapal doa supaya masuk kelas tepat waktu.
***
Benar saja, ketika memasuki gerbang, ia telah disambut dengan barisan siswa-siswa yang telat seperti ular yang melingkar. Dika berhenti sejenak lalu menghela napas. Lalu ia ikut baris juga di belakang orang paling terakhir yang ada di barisan itu.
Barisan menuju pada satu titik. Apa lagi kalau bukan pos jaga piket. Sudah ada dua orang guru yang akan mengintrogasi dan memberi surat izin masuk karena terlambat. Paling alasan yang dilontarkan siswa juga itu itu lagi. Kesiangan ... macet ... ban bocor ... lupa ada sekolah ....
Setelah berhasil melewati kendala sebelumnya, Dika harus siap berhadapan dengan guru yang sudah masuk kelas. Perlahan tapi pasti ia mendekati pintu dan melihat situasi. Waduh, lupa kalau jam pertama sama guru killer. Katanya ada “mati” dalam kata “matematika”.
“Asalamualaikum, Pak,” sapa Dika sambil mengetuk pintu kelasnya yang terbuka. Wajahnya dibuat mengkhawatirkan. Gerak-geriknya ia pastikan sopan. Berharap ada keajaiban pagi ini setelah hal-hal yang tak diharapkannya bermunculan.
“Siapa kamu?” jawab guru itu ketus.
“Siswa kelas ini, Pak. Boleh masuk?”
“Sini kamu.”
Ia pun memasuki kelasnya perlahan.
“Tau sekarang jam berapa?”
“Jam 8, Pak.”
“Buat apa kamu pake jam tangan bagus kalau sering telat?”
“Saya cuman kali ini telat pelajaran Papa.”
“Coba lihat teman-teman kamu.”
Dika menghadapkan tubuhnya pada seisi kelas. Pandangannya beralih dari lantai menjadi wajah teman-temannya, terlebih Daffa dan Tama yang sudah duduk sebangku. Ekspresi datar mendominasi semuanya, cari aman adalah kunci lulus dari mata pelajaran Matematika.
“Mereka bisa kok datang tepat waktu. Siapa nama kamu?”
“Dika, Pak.”
“Coba saya tanya sama kalian, Dika ini memang sering telat?” tanya Pak Bowo tegas sambil memandang murid seisi kelas dan menunjuk Dika.
Nggak ada yang berani mengeluarkan satu kata kecuali Pak Bowo. Beberapa ada yang menunduk. Beberapa mata lain ada yang melihat simpati.
“Ya udah, duduk kamu di situ,” pungkas Pak Bowo akhirnya.
Dika lega tapi juga merasa tak nyaman selama pelajaran berlangsung. Pasalnya ia seperti merasa telah dipermalukan di depan umum. Begitu pun ia tak bisa memilih tempat duduknya sendiri pada pelajaran itu. Hanya bangku kosong yang menemaninya, pasalnya salah satu teman kelasnya ada yang sakit, jadi tak semua bangku terisi. Sebelum berjalan pasrah ke mejanya, ia tersenyum tipis kepada kedua sohibnya, Daffa dan Tama hanya membalas lewat tatapan, mungkin ada kata-kata “sabar ya” yang menyembul keluar dari kepala Daffa layaknya awan-awan dialog pada komik-komik.
***
Akhirnya bel istirahat berbunyi. Setelah Pak Bowo keluar, beberapa teman cowok lainnya menepuk bahu belakang Dika untuk memberinya semangat, sebelum mereka keluar menuju kantin.
“Doohh Dika udah dikasih ujian kesabaran aja ya pagi-pagi,” celetuk Daffa ketika sampai di mejanya.
“Yah gimana lagi, Daf. Gara-gara begadang terus telat bangun sih.”
“Ngapain begadang? Ngerjain tugas? Nggak dicicil emang sebelumnya, Dik?”
“Heleh bisa aja ngomong gitu, emang sendirinya suka nyicil tugas?”
Daffa cuman nyengir. “Yang penting beres dengan cara yang halal dan nggak begadang sampai kesiangan.”
“Sialan.”
“Peace peace.”
“Nih, Dik.” Tama tiba-tiba menghampiri mereka sambil menyodorkan sebungkus roti dan sebotol air mineral.
“Wih, ditraktir Tama nih?” sahut Daffa dengan mata berbinar.
“Buat Dika doang, kalau kurang, beli sendiri sana.”
“Hem ... iya deh, kasian juga sama si Dika. Ke kantin dulu ah, ke sana lagi yuk, Tam? Dika mau beli yang lain juga nggak?”
“Nggak ah, baru dari kantin tadi sama si Andi, cuman pas mau balik ke sini lagi dia dipanggil ke ruang guru, ” balas Tama.
“Nggak deh lagi nggak mood, Daf,” balas Dika.
“Ya udah deh, duluan. Semangat oi!” pungkas Daffa sambil mengepalkan kedua tangan di hadapan Dika seakan menjadi pelatih tinju yang menyemangati anak muridnya sebelum tanding.
Tama lalu duduk di sebelah Dika dan memakan jajanannya. Baru aja mereka mulai makan dan berbincang ringan. Andi yang baru masuk kelas menghampiri meja mereka.
“Dik, tadi kata Bu Nia kamu disuruh ke ruang guru, temui Bu Nia.”
Dika yang baru mengunyah beberapa kali pun langsung cepat-cepat menelan dan minum.
“Oh iya? Makasih, Di.”
“Yo, sama-sama.”
***
Setelah mengetuk pintu beberapa kali dan terdengar sahutan “masuk” dari dalam, Dika memasuki ruang guru lantai dasar. Ruangannya cukup besar dengan cat berwarna putih dan penerangan yang cukup dari jendela dan lampu yang menggantung. Kubikel-kubikel yang diberi sekat antarkubikel menjadi markas para guru. Di sisi lainnya ada ruang untuk menerima tamu sekaligus bercengkerama antarguru. Berbeda dari riuh kantin, ruangan ini lebih tenang, kebanyakan guru keluar untuk makan, beberapa ada yang membereskan berkas, sisanya kosong. Dika mengamati suasana sambil berjalan santai menuju kubikel Bu Nia, guru bahasa Indonesia termasuk wali kelasnya.
“Asalamualaikum, Bu,” sapa Dika sopan sambil sedikit membungkuk ketika sampai di meja Bu Nia.
“Wa ‘alaikumus-salam, duduk, Dik,” balas Bu Nia sambil senyum dan menunjuk kursi di depannya dengan tangan menjulur dan telapak terbuka.
“Gimana kabarmu?”
“Baik, Bu.”
“To the point aja ya, Dik. Kayaknya ada yang beda sama kamu, biasanya seorang Dika selalu bersinar, akhir-akhir ini kayaknya agak redup, apa ada sesuatu yang bisa kamu bagi sama Ibu? Beberapa guru bilang kamu sering nggak fokus, nilaimu nggak secemerlang semester kemarin-kemarin, padahal sejak tahun pertama, kamu jadi kandidat juara kelas terus ya, Dik.”
Dika tersenyum mendengarnya, seakan ia sudah diberi rangkuman atas perilakunya akhir-akhir ini. “Saya merasa hilang motivasi aja, Bu. Merasa kehilangan diri sendiri dan bingung apa yang saya mau atau apa yang ingin saya tunjukkan.”
“Wah, udah agak berat ya pemikiran kamu. Memangnya apa yang kamu suka?”
“Saya suka baca fiksi sih, Bu. Cuman rasanya agak dipandang aneh kalau seorang cowok suka baca fiksi. Padahal kebanyakan sastrawan terkenal itu laki-laki. Senang aja rasanya berdiam diri sambil merasakan sekeliling saya dalam indra yang dipertajam, merasa lebih hidup gitu loh, Bu. Saya kepikiran masuk dunia industri kreatif, jadi apa aja deh asal berkaitan sama seni.”
“Keren tuh, bisa ngobrol banyak sama Ibu,” balas Bu Nia sambil sedikit tertawa, Dika pun mulai merasa nyaman dan akrab.
“Tapi orang tua saya belum sepemikiran, mereka lebih merasa aman kalau saya masuk bidang yang kebanyakan orang berpikir kalau terjun di dunia sana lebih menjanjikan.”
“Hmm, saya ngerti. Emang hidup selalu ada aja rintangannya, kalau lurus-lurus aja, bukan hidup namanya. Duh, saya jadi keinget kata-kata ayah. Nggak apa-apa, Dik. Coba kamu rasakan dan pikirkan lagi, apa kamu udah yakin? Kalau kamu sendiri udah yakin banget, coba yakinkan orang-orang sekitarmu terlebih orang tuamu. Sebenarnya mereka hanya perlu diyakinkan dan dijelaskan alasan-alasannya. Semoga perjalananmu lancar. Ibu selalu doakan yang terbaik.”
“Wah, makasih banyak sarannya, Bu.”
“Selain itu sebenarnya Ibu mau ngasih tau pengumuman lain. Tadi Pak Bowo titip pesan sama Ibu, katanya nanti udah pulang sekolah kamu ke ruang guru lagi ya, temui Pak Bima, buat remedial Fisika.”
“Oh iya ... saya remedial, Bu? Kenapa tadi Pak Prabowo nggak bilang langsung pas di kelas, ya?”
“Tadi sehabis ngajar di kelas kalian, Pak Bowo ke ruang guru terus langsung pergi keluar kota, beliau ngobrol sama saya sambil beres-beres, sekalian ceritain tentang kamu. Beliau merasa khilaf dan bersalah sudah mempermalukan kamu tadi di kelas karena terlambat dan nggak mau mempermalukan kamu lagi karena remedial sendirian. Mungkin beliau bakal ngobrol langsung lagi sama kamu. Ibu cuman menyampaikan amanatnya.”
“Oh begitu ... baik, Bu. Terima kasih.”
“Semangat ya, Dika. Entar remednya cuman membetulkan jawaban kemarin yang salah, kamu bisa tanya-tanya lagi ke teman-teman. Entar udah beres remed, lupain aja. Fokus lagi ke depan dan pada waktu ‘sekarang’. Nggak ada yang bisa jago di semua bidang sekaligus, kalaupun ada, yang benar-benar bisa kita maksimalkan mungkin hanya satu atau dua. Jadi expert di bidang yang kamu suka. Kembangkan kemampuan terbaikmu. Kamu udah jago loh di pelajaran Ibu. Pokoknya tetap semangat!” Bu Nia menyemangati Dika sambil tersenyum dan mengepalkan kedua tangannya.
“Wah, makasih banyak ya, Bu. Doakan Dika terus ya,” balas Dika yang berusaha lebih positif setelah mendengar suntikan-suntikan semangat wali kelasnya.
***
Hari itu berjalan cepat tanpa terasa. Sudah waktunya pulang lagi. Waktunya Dika remedial sendirian di ruang guru ditemani Pak Bima. Teman-teman kelasnya yang tahu Dika remedial memberi semangat dan membantu mengajarinya. Termasuk Daffa dan Tama yang selalu ada saat-saat dirinya di atas roda kehidupan maupun di bawahnya. Ya ... memang sedih sih, tapi kehidupan harus terus berlanjut, bukan? Dengan sisa-sisa harapan, hari itu Dika akhirnya menyelesaikan tugasnya sebagai siswa SMA. Sekarang waktunya pulang ke rumah.
***
Dika mengembuskan napas lega, hari sebentar lagi berakhir, langit jingga bercampur biru sisa-sisa langit tadi siang melukis atmosfer bumi. Ia bisa melihat matahari perlahan-lahan sembunyi di balik awan ketika menengadahkan pandangannya. Gerbang sekolah yang baru dilaluinya pun tak tampak lagi barisan mengular anak-anak yang telat datang, hampir semua penghuni sekolah sudah pulang.
Sepeda motornya meluncur ringan, melewati kendaraan-kendaraan yang kini sedang bermuara ke tempat tinggal pemiliknya. Tak lama kemudian, langit tak hanya dipenuhi suara deru kendaraan, tetapi juga rintikan air yang semakin lama semakin deras. Dika mulai awas lagi, ia mempercepat laju motornya, rumahnya masih cukup jauh. Namun, kecepatan rintik hujan lebih cepat melesat, bagai anak panah yang ditembakkan oleh beratus atlet panahan. Mau tak mau, Dika mencari tempat berteduh.
***
Hujan besar kali itu lebih lama dari biasanya. Hampir dua jam Dika menunggu, lama-lama perasaannya mulai goyah, yang asalnya sudah positif mendengar penyemangat Bu Nia, kini aura-aura negatif seakan menggodanya karena tak rela ia bisa menerima kejadian-kejadian yang tak diharapkannya. Akhirnya Dika membuka ponsel yang sebentar lagi mati karena lowbat. Langsung ia mengabari ibunya kalau terjebak hujan, lalu membuka obrolan grup dengan Daffa dan Tama.
Dika: Hari menyebalkan belum berakhir, kejebak hujan udah dua jam nih.
Daffa: Seriusan? Adoh sabar sabar. Orang sabar jodohnya cantik.
Tama: Di mana, Dik?
Dika: Aamiin, ye Daf. Di belokan Jalan Angkasa, Tam.
Tama: Lah? Deket rumah dong?
Maksudnya dekat rumah Tama. Saat itu Dika baru ngeh dan langsung menepuk dahinya ketika membaca chat dari Tama. Kenapa dari tadi nggak kepikiran, ya? Hari ini kenapa sih, Dik.
Dika: Lah iya, baru ngeh masa. Entar mau mampir ke rumah deh, ya?
Tama: Iya sini aja dulu, Dik. Kasian amat hari ini hahaha.
***
Setelah itu Dika mampir dulu ke rumah Tama. Meskipun masih hujan, tapi untungnya tinggal gerimis. Ibunya Tama baik banget. Baru aja masuk ke rumah dan saling mengucap salam, Dika langsung diperlakukan kayak anak sendiri, dikasih makan dan minuman hangat.
“Duh ini anak pinter yang pernah disebut sama neneknya Tama habis kehujanan, habisin makanannya ya, minum juga tehnya biar anget, Dik.”
“Hehe iya makasih, Bu. Oh iya nenek Tama juga pernah ceritain Dika ke Ibu?”
“Iyaa, neneknya Tama kayaknya suka banget sama kamu, anak baik dan bakal jadi anak sukses katanya, kalau bisa mah mungkin kamu diangkat jadi cucu hahaha.” Begitulah ibunya Tama, ceriwisnya keluar. Dika dan Tama balas tertawa kecil.
“Kata nenek, kamu tuh peka sama lingkungan, tapi lebih ke alam sama benda-benda yang biasanya luput sama perhatian manusia,” tambah Tama memuji Dika.
“Aduduh kelamaan di sini bisa-bisa terbang hahaha, makasih makasih,” balas Dika yang sebenarnya malu dipuji terus, tapi sekaligus merasa bersyukur karena masih ada yang menghibur saat harinya nggak secerah biasanya.
“Oh, iya? Jangan-jangan kamu suka nulis sama baca buku, Dik?” tanya ibu Tama sambil mencomot tahu hangat di depannya, mereka sedang duduk bersama di meja makan.
“Ya ... suka sih, Bu.”
“Bagus tuh, jarang-jarang sekarang yang suka baca atau nulis gitu, kebanyakan seneng senam jempol nulis status sosmed,” ujar ibunya Tama kemudian tertawa lagi akibat omongannya sendiri. “Suka ikut lomba-lomba gitu?”
“Ehm ... belum sih, Bu—” jawab Dika terpotong Tama.
“Dika mah masih malu-malu nunjukkin bakatnya. Cobain gih kalau ada lomba.”
“Oh iyaaa, coba tuh, ada om-nya Tama yang punya penerbit buku indie, suka ngadain lomba-lomba gitu, cobain deh, Dik. Entar juga kalau ada lowongan kerja di sana, kamu bisa ibu rekomendasiin, tenang aja Dik, soal rezeki jangan dipikirin, fokus sama kemampuan kamu, go go go Dikaaa pasti bisaaa!” ujar ibunya Tama lagi. Dika jadi tersenyum lagi. Banyak hal-hal yang sering luput untuk disyukuri, bahkan hal sederhana sekalipun, seperti kehadiran orang-orang yang mendukungnya.
***
Karena takut kemalaman, Dika akhirnya pamit pulang. Namun, tiba-tiba sepeda motornya nggak bisa nyala. Akhirnya Dika diantar pulang sama Tama. Sesampainya di rumah Dika ....
“Duh, Tam, makasih banyak ya, ngerepotin mulu nih.”
“Santai aja, Dik, kalau ada apa-apa bilang aja, kita-kita bakal selalu ada, insyaallah.”
Setelah mengucap terima kasih sekali lagi, Tama langsung pulang. Dika langsung disambut ibunya, ngobrol sebentar, dibuatkan cokelat panas, bersih-bersih, lalu istirahat di kamarnya, hari ini benar-benar berakhir. Semoga besok harapan yang baru terbit lagi. Sebelum memejamkan matanya, ia meraih buku coret-coretnya yang tergeletak di atas meja, lalu mulai menulis lagi.
Untukmu
Saat musim hujan.
Hai kamu—diriku sendiri. Ingat dan bacalah ini jika harimu terasa sangat menyedihkan.
Kamu harus percaya bisa bahagia karena ....
Tuhan selalu ada untukmu dan nikmatnya tak terkira. Tuhan akan selalu mendengarkanmu di saat tak ada telinga manusia yang ingin menanggapinya. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, berbaiksangkalah kepada-Nya atas segala yang terjadi.
Orang tuamu masih dan akan selalu ada. Mereka akan melakukan apa saja untukmu. Ingat, mereka tidak pernah mengeluh memberi segala yang kamu minta. Mereka memberikan segala-galanya untuk kamu. Mereka lebih memilih peduli terhadapmu daripada diri mereka sendiri. Apa kamu tidak ingat lagi?
Keluarga dan sahabat yang menerima, mendukung, dan menyemangatimu. Siapa lagi yang mau mendengar celoteh tidak penting, tertawa lepas, atau menghabiskan waktu bersamamu kalau bukan mereka. Bersyukurlah mereka masih ada untukmu.
Percaya juga pada setiap sel dari fungsi tubuhmu. Kamu harus ingat bahwa sistem tubuhmu itu sangat rumit. Setiap jutaan sel dan neuron masih berfungsi dengan baik setiap detiknya. Semua bagian terkecil dari tubuhmu tetap bekerja demi kesehatanmu. Apa kamu tidak tahu?
Percaya juga pada cita-citamu. Percaya pada hal yang kamu sukai. Percaya bahwa itulah salah satu tujuan hidupmu. Raih dan bersemangatlah mewujudkannya. Jangan pernah menyerah meskipun sampai berdarah-darah.
Jika seandainya kamu sudah tidak punya semua hal itu, setidaknya kamu masih hidup, dan tidak mungkin semuanya lenyap karena Tuhan tidak sekejam itu.
Terakhir, kamu harus percaya kalau kamu bisa sayangi dirimu sendiri di saat orang lain juga bisa menyayangimu. Maka dari itu, sekarang lupakan dan maafkan segala hal yang membuatmu bersedih. Tersenyum dan berbahagialah karena jantung dan paru-parumu tidak bisa dipakai dua kali.
Tetes hujan terakhir,
M.


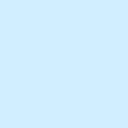 cantikahanah
cantikahanah






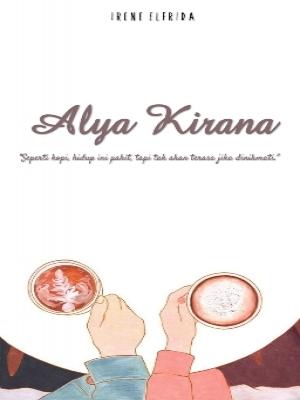




Mantap cantikaaa, teruskan ya semoga jalan menjadi penulis lancar sukses dan dapat memberikan inspirasi lewat tulisanmu seperti yang udah kamu lakukan padaku.
Comment on chapter 1. Gerbang Masa Lalu